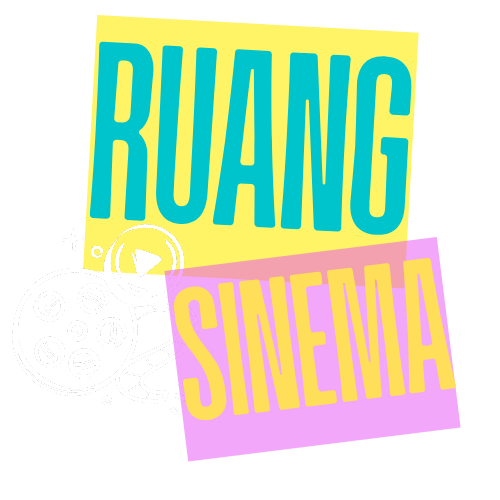Mari kita mulai dari yang paling penting: Mendadak Dangdut versi 2025 bukan sekadar “reboot“. Ia adalah upaya ambisius—kadang terlalu ambisius—untuk menjadikan dangdut lebih dari sekadar genre musik, tapi sebagai cultural power move. Sayangnya, seperti goyangan yang terlalu semangat di panggung sempit, film ini sesekali kehilangan pijakan.
Secara permukaan, film ini berhasil membangun daya tarik massal: komedi receh tapi efektif, soundtrack yang bisa membuatmu spontan nyanyi “Jablay” di bioskop (dan tak malu soal itu), dan tentu saja, visual yang diminyaki filter sinetron premium. Keanu Angelo dan Opie Kumis menciptakan dinamika absurd yang entah kenapa cocok, sedangkan Anya Geraldine—yang awalnya terlihat salah casting—secara mengejutkan punya “weight” emosional yang cukup buat menggendong separuh konflik film.
Tapi mari kita kulik lapisan dalamnya. Film ini mencoba bicara banyak: tentang stigma perempuan di dunia hiburan, represi sosial, bahkan trauma personal. Namun bukannya fokus pada satu isu, ia malah menjejalkan semua jadi satu. Hasilnya, kita dapat naskah yang seperti utas Twitter belum diedit: banyak poin menarik tapi minim kohesi. (Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik atau koheren).

Gaya penceritaannya sendiri cenderung fragmentaris. Perpindahan adegan kadang terlalu cepat, subplot tumbuh seperti rumput liar, dan karakter-karakter pendukung hanya eksis sebagai alat pendorong alur, bukan tokoh dengan kedalaman. Ironis, mengingat film ini justru ingin memberi napas segar lewat “kompleksitas”.
Namun yang paling mencolok—dan mungkin disengaja—adalah keberanian film ini mempermainkan estetika dangdut. Bukan lagi panggung koplo murahan, tapi dangdut yang dibungkus dalam kemasan pop-sosial, digabung EDM, dan bahkan disentuh kritik kelas sosial. Di titik ini, film ini sukses: ia membawa dangdut dari pinggir jalan ke meja diskusi cafe-cafe SCBD. Tapi ketika penonton mulai bertanya “so what?”, film ini tidak benar-benar punya jawaban.
Ada juga kegagalan subtil yang harus dicatat: representasi perempuan. Tokoh perempuan dalam film ini, meski kelihatan kuat dan lantang, sering tetap disetir narasi patriarkis yang dibungkus rapi. Ketika sang penyanyi dihadapkan pada konflik, solusinya masih datang dari luar dirinya—entah pria, panggung, atau skandal. Emansipasi semu, disajikan dalam bungkus empowerment palsu.
Kesimpulannya? Mendadak Dangdut 2025 adalah potensi besar yang belum masak. Ia punya niat mulia dan keberanian genre-bending, tapi terjebak antara ingin menyenangkan semua pihak dan menjadi kritik budaya tajam. Hasilnya seperti konser dangdut di acara nikahan: seru, riuh, kadang menyentuh, tapi tetap dikendalikan panitia.