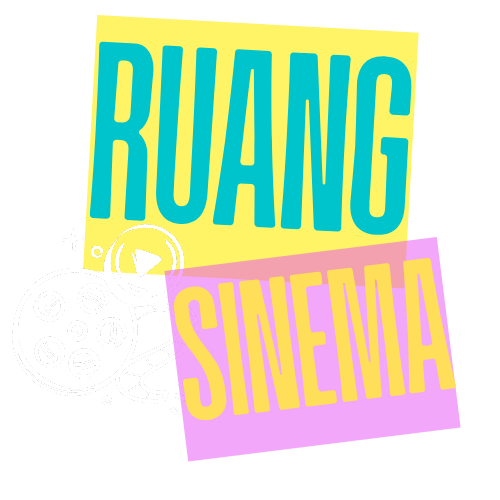Di tengah kebangkitan film horor Indonesia yang seolah menjadi jaminan laris di box office, Pencarian Terakhir (2025) hadir sebagai upaya nostalgia sekaligus sekuel dari film berjudul sama yang rilis pada 2008. Namun, alih-alih memperlihatkan kematangan artistik setelah 17 tahun berselang, film arahan Affandi Abdul Rachman ini justru terjebak dalam kabut euforia industri yang terlalu yakin bahwa “asal horor, pasti laku.”
Sejatinya, film pertamanya memiliki kekuatan naratif yang sederhana namun solid: sebuah misi pencarian dan penyelamatan korban hilang di gunung. Ketegangan dibangun dari interaksi manusia dengan alam, dibalut atmosfer realistis yang dekat dengan pengalaman nyata para pendaki. Ada nilai dokumenter, ada penghormatan terhadap risiko nyata, dan ada narasi penyelamatan yang kuat. Sementara itu, Pencarian Terakhir (2025) meninggalkan akar kejujurannya. Ia menggeser inti misi pencarian menjadi sekadar tempelan, dan terlalu terbuai pada mistifikasi gunung demi memuaskan selera penonton horor kekinian.
Plot yang Tersandung
Kisah dimulai dari hilangnya Sita (Artika Sari Devi) di Gunung Sarangan ketika sedang merayakan ulang tahun putrinya. Bertahun kemudian, Drupadi (Adzana Ashel) melakukan pendakian untuk mencari sang ibu, ditemani sahabat dan kekasihnya. Sebuah premis yang seharusnya bisa menggali konflik emosional dan spiritual keluarga. Namun dalam eksekusinya, film terlalu sibuk menjejalkan elemen mistis dan jumpscare generik, hingga tensi personal itu tak pernah mencapai kedalaman yang berarti.
Alur cerita yang harusnya menghadirkan dilema psikologis antara trauma seorang ayah (Donny Alamsyah), tekad seorang anak (Adzana Ashel), dan misteri hilangnya seorang ibu, justru dikerdilkan menjadi parade ketegangan instan. Penutup cerita pun tampak terburu-buru, seakan film kehabisan energi untuk merajut resolusi yang memuaskan.
Jumpscare Klise, Sound yang Berisik
Secara teknis, film ini memang menampilkan atmosfer visual yang cukup meyakinkan: kabut, rimba, dan kegelapan gunung divisualisasikan dengan sinematografi yang indah. Sayangnya, indah tidak selalu berarti efektif. Terlalu banyak mengandalkan jumpscare yang mudah ditebak, film kehilangan kesempatan untuk membangun horor dari atmosfer, bukan sekadar dari dentuman keras.
Lebih buruk lagi, tata suara justru menghancurkan potensi atmosfer tersebut. Alih-alih membangun suasana mencekam dengan subtilitas, film ini memilih jalan pintas dengan ledakan suara keras yang memekakkan telinga. Ketika setiap ketegangan selalu diiringi dengan teriakan sound effect, alih-alih takut, penonton hanya merasa terganggu.
Akting yang Pincang, Chemistry yang Absen
Dari segi akting, kelemahan film ini makin jelas. Para pemain tampak berdiri sendiri, seolah-olah tidak pernah melalui proses pembacaan naskah atau pendalaman karakter secara serius. Chemistry nyaris nihil, terutama antar anggota kelompok pendakian yang seharusnya memperlihatkan ikatan emosional kuat.
Fatih Unru, aktor muda yang selama ini dikenal penuh energi dan detail dalam membangun karakter, tampil mengecewakan. Performanya seperti tidak diarahkan, gersang, bahkan kadang terasa setengah hati. Inilah catatan buruk yang sangat disayangkan. Sebaliknya, penampilan singkat Artika Sari Devi justru menjadi cahaya di tengah kegelapan film ini. Aura misteriusnya mampu mencuri perhatian dan memberikan kedalaman emosional yang nyaris absen pada pemain lain.
Dari Drama Keluarga Menjadi Tren Horor
Ada pergeseran mendasar yang menjadikan Pencarian Terakhir (2025) lebih lemah daripada pendahulunya. Film tahun 2008 berdiri di atas fondasi realisme: sebuah keluarga menghadapi tragedi di alam bebas. Film terbaru ini, sebaliknya, lebih sibuk mengejar tren. Alih-alih mempertajam drama keluarga dan perjuangan melawan alam, ia memilih jalan pintas: membangun kengerian artifisial lewat mitos gunung dan penampakan mistis.
Ketika film pertama menekankan keberanian tim SAR, semangat gotong royong, dan ketegangan realistis sebuah misi pencarian, film kedua ini seolah lupa daratan. Ia ingin tampil sebagai horor spektakuler, tapi justru kehilangan keotentikan dan empati.
Kritik Tajam untuk Sutradara dan Produksi
Kesalahan terbesar film ini terletak pada penyutradaraan yang lalai. Affandi Abdul Rachman tampak terjebak pada kalkulasi pasar. Ia seperti lebih tertarik untuk ikut arus tren ketimbang mengukuhkan identitas artistik filmnya. Hasilnya adalah film yang setengah matang: visual lumayan, premis menjanjikan, tapi eksekusi penuh kelemahan.
Kekurangan ini diperparah oleh produksi yang tampak tidak memberi perhatian serius pada detail akting maupun integrasi tim pemain. Film horor seharusnya tidak hanya menakut-nakuti; ia harus membangun dunia yang meyakinkan agar ketakutan itu masuk akal. Sayangnya, di sini kita hanya disuguhi kepalsuan yang mencolok.
Kesimpulan
Pencarian Terakhir (2025) adalah contoh jelas bagaimana sebuah sekuel bisa gagal menghormati sumbernya. Alih-alih berkembang, film ini mundur beberapa langkah. Ia kehilangan arah, kehilangan kejujuran, dan kehilangan daya pikat emosional yang semestinya hadir.
Kritik paling pedas: film ini hanyalah produk euforia industri, bukan karya yang lahir dari kedalaman artistik. Sebuah tontonan yang mungkin masih menghibur bagi penonton awam pecinta jumpscare, namun bagi mereka yang mengharapkan sebuah karya horor dengan substansi, film ini terasa sebagai pencarian yang benar-benar tersesat.