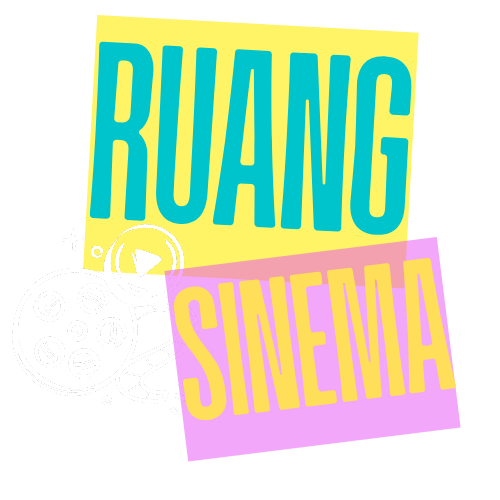Kadang, niat baik dalam film bisa jadi bumerang ketika ambisinya nggak diimbangi kemampuan bercerita yang solid. Itu yang terasa banget saat menonton Sayap-Sayap Patah 2: Olivia—film sekuel yang katanya ingin bicara tentang luka masa lalu, beban keluarga, dan pilihan hidup yang kelam, tapi malah seperti tersesat di tengah angin narasi yang kencang.
Di atas kertas, film ini punya premis yang menggoda. Ada dua garis cerita yang berusaha dibangun: satu tentang seorang ayah yang bekerja sebagai polisi sekaligus single father, dan satu lagi tentang anak muda yang terjebak dalam bayang-bayang masa lalu ayahnya yang pernah terlibat dalam jaringan kekerasan ideologis. Dua konflik personal yang sebenarnya kuat secara tematik, tapi sayangnya justru saling menenggelamkan.
Alih-alih saling menguatkan, dua plot ini malah seperti dua kaki yang nggak pernah jalan bareng. Satu langkah ke kiri, satu lagi ke kanan. Hasilnya? Penonton terseret dalam pacing yang lambat, karakter yang tipis, dan drama yang nggak pernah benar-benar menyentuh.

Olivia yang Hilang di Judulnya
Satu hal yang paling bikin bingung adalah keputusan untuk menggunakan nama Olivia di judul, padahal karakter ini sudah meninggal dan kemunculannya di film sangat minimal. Bukannya jadi semacam benang merah emosional atau simbol trauma kolektif, kehadiran Olivia justru terasa seperti gimmick pemasaran. Seolah-olah filmnya sendiri belum yakin cerita utamanya cukup kuat tanpa embel-embel itu.
Yang lebih membingungkan lagi, nama Olivia tidak pernah betul-betul diurai dalam narasi. Tidak ada momen yang membangun keterikatan emosional dengan tokoh ini, tidak ada scene kunci yang membuat penonton bisa ikut merasa kehilangan atau rindu. Yang ada malah serangkaian adegan setengah matang yang seolah meminta kita memahami trauma tanpa diajak masuk ke dalamnya.
Akting: Bio One Bersinar, Arya Saloka Masih Nyangkut di Sinetron
Di tengah kekacauan alur dan pacing yang semrawut, salah satu penyelamat film ini mungkin adalah Bio One. Ia bermain dengan cukup intens, terutama dalam menggambarkan kebimbangan anak muda yang berusaha keluar dari warisan gelap ayahnya. Emosinya rapi, gesture-nya nggak lebay, dan ekspresinya nyaris selalu tepat sasaran. Kalau boleh jujur, karakter Bio One-lah yang bikin film ini masih bisa ditonton tanpa memicingkan mata terus-menerus.
Sebaliknya, Arya Saloka justru tampil seperti masih tersangkut dalam dunia sinetron prime time. Ekspresinya repetitif, dan cara ia menyampaikan emosi terasa seperti template dari satu episode ke episode berikutnya. Tidak ada momen eksplorasi emosional yang berani, tidak ada improvisasi yang menggugah. Chemistry-nya dengan Myesha pun hambar, nyaris tak berdenyut. Kalau ini seharusnya jadi hubungan ayah-anak yang rumit dan penuh konflik batin, maka gagal total. Yang muncul hanya dua karakter yang sama-sama capek, tapi bukan karena konflik—karena naskahnya aja yang nggak kasih mereka ruang berkembang.Sayang sekali.
Visual Layak, Tapi Tidak Cukup
Secara teknis, Sayap-Sayap Patah 2: Olivia sebenarnya tidak buruk. Beberapa adegan memiliki sinematografi yang cukup rapi, pencahayaan yang tepat, dan audio yang bersih. Tapi visual hanya bisa membantu sejauh naskahnya mendukung. Dan di sinilah masalah terbesar film ini: tidak tahu harus dibawa ke mana.
Pacing di paruh awal sangat lambat dan membosankan, hanya sedikit meningkat di sepertiga akhir ketika konflik mulai terasa memuncak. Tapi karena dari awal penonton tidak diajak untuk peduli, ketika momen dramatis datang pun kita sudah terlalu lelah untuk ikut tenggelam. Emosi yang seharusnya menghantam justru hanya lewat seperti angin AC di bioskop.
Penutup: Sebuah Sayap yang Belum Siap Terbang
Sayap-Sayap Patah 2: Olivia sebenarnya punya niat baik—mengangkat isu tentang kekerasan ideologis, trauma keluarga, dan pertarungan batin antargenerasi. Tapi semua itu tenggelam dalam eksekusi yang lemah, karakterisasi yang mentah, dan akting yang tidak lepas dari bayang-bayang sinetron. Film ini seperti burung yang ingin terbang tinggi, tapi sayapnya masih basah dan berat oleh ambisi yang tidak terarah.
Kalau kamu penonton yang ingin digugah, disentuh, atau sekadar dibikin penasaran, film ini mungkin akan terasa seperti perjalanan yang membingungkan dan kurang memuaskan. Tapi kalau kamu fans garis keras Bio One—well, mungkin kamu bisa sedikit memaafkan.