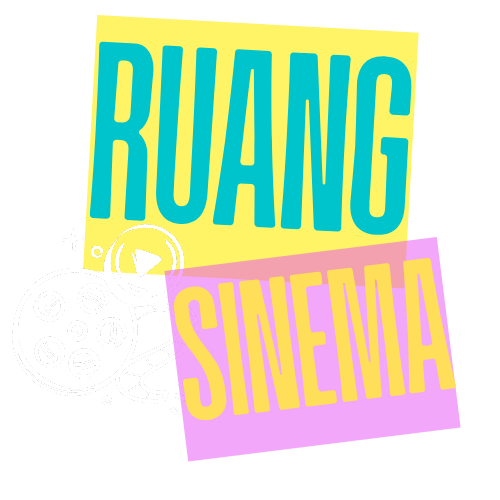“Bertaut Rindu” adalah contoh gamblang dari film yang begitu ingin terlihat dalam, namun lupa bagaimana cara menyelam. Sebuah drama remaja yang membawa isu trauma keluarga, tekanan batin, dan mimpi yang dirampas orang tua, tapi tak satu pun dari elemen itu benar-benar digali. Ia seperti lukisan realis yang cantik dari jauh, tapi saat didekati, yang terlihat hanya goresan tipis yang tak selesai.
Disutradarai oleh Rako Prijanto, film ini menempatkan Adhisty Zara sebagai Jovanka, remaja enerjik dan vokal, berseberangan dengan Ari Irham sebagai Magnus, pemuda tertutup yang memikul ekspektasi keluarga seperti batu yang menghimpit dada. Premisnya menjanjikan: dua jiwa muda, sama-sama terluka, saling menemukan dan mencoba saling menyembuhkan. Tapi janji itu cepat gugur, karena film ini hanya menyentuh permukaan, takut menelusuri akar luka yang sebenarnya.

Karakterisasi menjadi titik lemah utama. Jovanka ditulis dengan cara yang terlalu stereotipikal—ceria, cerewet, impulsif—tanpa ruang untuk kompleksitas. Magnus pun tak lebih dari siluet karakter introvert yang berjalan dengan ekspresi mendung dan tatapan kosong. Relasi mereka tumbuh cepat, tanpa gesekan atau dinamika emosi yang nyata. Alih-alih membangun koneksi lewat konflik dan pengertian, mereka lebih banyak bertukar kalimat indah yang terdengar seperti kutipan dari laman motivasi remaja di Instagram.
Dialog yang kaku memperparah keterputusan emosi itu. Percakapan antara karakter terasa dibuat-buat, seolah-olah setiap kata sudah disterilkan dari kemungkinan spontanitas. Ketika dua karakter muda dengan luka emosional saling bicara, seharusnya ada kegugupan, kemarahan, atau kejujuran yang tidak rapi. Tapi “Bertaut Rindu” memilih jalan paling aman: membungkus rasa sakit dengan kata-kata sopan dan estetis. Seolah trauma hanya bisa hadir dalam warna pastel dan musik lembut.
Sialnya, film “Bertaut Rindu” juga gamang terhadap identitas dirinya. Ia ingin menjadi drama kontemplatif, tapi tak cukup berani. Ia ingin sedikit romantis, tapi tak punya tensi. Ia menyisipkan humor, tapi tak pernah benar-benar lucu. Hasilnya adalah film yang berjalan di antara banyak genre tanpa pernah benar-benar sampai di mana pun.
Secara visual, “Bertaut Rindu” memang sedap dipandang. Tata warna hangat, komposisi gambar rapi, dan ritme sinematik yang terkontrol. Tapi semua itu hanya lapisan kulit. Tidak ada daging, apalagi tulang. Sinema bukan hanya tentang bagaimana gambar diproyeksikan, tapi juga tentang apa yang digumamkan dalam diam. Dan dalam diam-diamnya, film ini tak mengatakan apa pun yang sungguh berarti.
Adhisty Zara dan Ari Irham menampilkan upaya yang patut dihargai, tapi upaya itu tak didukung oleh naskah yang bernyawa. Tak ada ruang bagi mereka untuk bermain-main dengan emosi yang mentah atau labil. Semua sudah diatur rapi, dibersihkan dari potensi konfrontasi emosional, dan akhirnya terasa artifisial. Tak satu pun dari adegan puncaknya terasa meledak atau mengendap.
Yang paling disayangkan dari “Bertaut Rindu” adalah keberpura-puraannya dalam menangani isu besar seperti kesehatan mental dan tekanan sosial dalam keluarga. Tema ini begitu penting dan relevan dalam konteks Indonesia hari ini, ketika banyak remaja tumbuh di bawah bayang-bayang ekspektasi generasi sebelumnya. Namun alih-alih menjadi ruang untuk refleksi kolektif, film ini justru menjadikan isu itu sebagai latar artistik semata. Ia menatap luka, tapi tidak pernah menyentuhnya. Apalagi merasakannya.
Dalam lanskap perfilman remaja Indonesia yang mulai berkembang, film ini seharusnya hadir sebagai pernyataan: bahwa generasi muda bukan sekadar estetik, tetapi juga kompleks dan penuh perlawanan batin. Bahwa tekanan keluarga bukan sekadar konflik generik, tetapi realitas struktural yang butuh diurai dengan keberanian. Sayangnya, “Bertaut Rindu” justru membungkam itu semua dalam kemasan visual yang terlalu bersih, terlalu indah, terlalu takut merusak tatanan rambut karakternya.
Dan di situlah letak ironi paling getir dari film ini: ia membawa luka, tapi tidak mau kotor. Ia bicara tentang trauma, tapi takut menangis dengan suara keras. Ia ingin dipuji dalam, padahal yang ditawarkan hanyalah kolam dangkal yang memantulkan bayangan sendiri.
“Bertaut Rindu” mungkin akan tetap dikenang sebagai film yang “niat baiknya besar.” Tapi niat, seperti halnya cinta dalam cerita ini, tak akan cukup kalau tak diikuti dengan keberanian. Karena dalam dunia sinema, kejujuran adalah nyawa. Dan film ini, sayangnya, terlalu rapi untuk hidup, terlalu aman untuk tumbuh, dan terlalu takut untuk benar-benar menyentuh apa yang selama ini ingin disuarakannya.