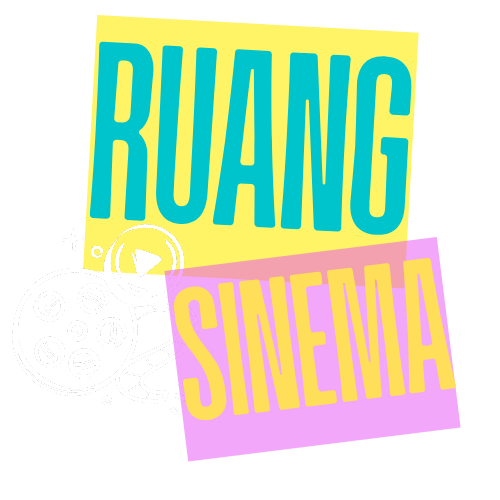Ada kalanya sebuah film tidak perlu berteriak untuk didengar. Hanya Namamu Dalam Doaku (2025), produksi terbaru Sinemaku Pictures, adalah contoh mutakhir tentang bagaimana sebuah drama keluarga bisa hadir dengan tenang namun meninggalkan jejak dalam yang sulit dihapus. Disutradarai Reka Wijaya, film ini mengambil jalan berisiko: menjauh dari melodrama klise perselingkuhan atau konflik domestik murahan, lalu menyoroti realitas yang jarang digarap dalam sinema Indonesia—perjuangan sebuah keluarga menghadapi penyakit langka, ALS, yang menggerogoti tubuh sang ayah, Arga (Vino G. Bastian).
Sejak awal, film ini menolak untuk tampil sensasional. Tidak ada eksposisi medis panjang lebar, tidak ada adegan dramatis yang digiring musik bombastis. Yang ada justru potongan keseharian keluarga yang tampak sederhana, bahkan rapuh, namun sesungguhnya menyimpan gejolak emosi yang menanti saatnya pecah. Pendekatan ini menghadirkan atmosfer intim: kamera kerap bertahan pada tatapan, hening, dan jeda—ruang di mana penonton dipaksa ikut menyelami beban batin karakter.
Pilar Emosi: Akting yang Membumi
Dalam konstruksi semacam ini, tentu aktor lah yang memikul beban terbesar. Vino G. Bastian tampil sebagai Arga dengan intensitas yang kompleks: keras kepala, kadang egois, namun sesungguhnya menyimpan ketakutan yang tak terucapkan. Ada yang menilai karakternya terlalu berat sebelah, namun justru dari “cacat” itulah manusiawinya muncul. Nirina Zubir, yang memerankan Hanggini, sekali lagi membuktikan konsistensi: performanya tidak pernah meledak-ledak, tetapi justru mengalir, menguras hati tanpa terasa dibuat-buat.
Anantya Kirana sebagai Nala membawa perspektif anak yang rentan, sementara kehadiran Naysilla Mirdad dan Dinda Kanya Dewi memperkaya tekstur kisah tanpa terasa sebagai tempelan. Menariknya, film ini berhasil mengawinkan dua “dialek” akting yang selama ini kerap dipisahkan: gaya sinetron yang ekspresif dengan pendekatan film yang subtil. Hasilnya sebuah ruang hibrid yang, walau berisiko timpang, di sini justru terasa menyatu.
Kesedihan Tanpa Paksaan
Salah satu keberhasilan terbesar film ini terletak pada bagaimana ia menolak jebakan melodrama murahan. Banyak film keluarga Indonesia kerap menggunakan musik sendu untuk mengarahkan emosi penonton. Hanya Namamu Dalam Doaku memilih jalur lain: kesedihan tumbuh dari percakapan kecil, dari senyum yang ditahan, dari genggaman tangan yang tak ingin dilepas. Inilah jenis kesedihan yang organik, tidak pernah menggurui, tidak pernah mendikte.
Namun, pendekatan subtil ini bukan tanpa risiko. Sebagian penonton mungkin merasakan film ini terlalu menahan diri, sehingga isu utama—bagaimana keluarga menghadapi tantangan merawat pasien ALS—kurang dieksplorasi secara utuh. Alih-alih menggali lebih dalam dinamika perawatan, film sempat terdistraksi oleh sub plot yang nyaris mengarah ke isu perselingkuhan, meski tidak pernah benar-benar jadi pusat cerita. Ketidaktegasan inilah yang sesekali membuat narasi goyah.
Teknis yang Terkurasi
Secara visual, film ini memilih estetika lembut: pencahayaan hangat, framing intim, dan ritme pengambilan gambar yang memberi ruang bagi penonton untuk bernapas. Tidak ada estetika berlebihan; kesunyian menjadi bahasa utama. Tata musik pun ditempatkan dengan hati-hati. Pilihan “Bahasa Kalbu” dari Raisa yang muncul pada momen krusial, misalnya, memberi resonansi emosional tanpa terasa manipulatif. Semua unsur teknis terasa ditakar dengan presisi, seakan ingin membuktikan bahwa kekuatan film ini memang bersumber dari rasa, bukan dari gaya.
Kritik yang Perlu Digarisbawahi
Meski banyak yang patut diapresiasi, film ini bukan tanpa kelemahan. Penulisan naskah terkadang goyah, terutama saat mencoba menyeimbangkan isu medis dengan drama keluarga. Alih-alih menyelam lebih dalam pada kompleksitas ALS dan bagaimana keluarga beradaptasi, naskah justru sesekali memberi ruang bagi konflik sampingan yang kurang relevan. Akibatnya, fokus cerita sempat kabur, dan potensi besar untuk menghadirkan narasi yang lebih menggugah malah sedikit tereduksi.
Selain itu, meski pendekatan “kesedihan tanpa paksaan” terasa segar, ia juga berisiko menimbulkan kesan datar bagi penonton yang menantikan ledakan emosional. Di sinilah dilema film ini: apa yang bagi sebagian orang terasa elegan, bagi yang lain bisa saja tampak kurang greget.
Kesimpulan: Sebuah Langkah Matang
Pada akhirnya, Hanya Namamu Dalam Doaku adalah pencapaian penting bagi Sinemaku Pictures. Film ini menolak untuk menjadi sekadar melodrama murahan, dan memilih untuk menghadirkan potret keluarga yang jujur, getir, sekaligus hangat. Ia mengingatkan bahwa keluarga tidak pernah sempurna; bahwa ujian justru bisa menjadi alasan untuk saling menguatkan.
Sebagai sebuah karya, film ini memang tidak sempurna. Tetapi justru dari ketidaksempurnaan itulah ia menemukan denyut kehidupannya. Dalam lanskap sinema Indonesia yang masih sering terjebak dalam pola repetitif, Hanya Namamu Dalam Doaku hadir sebagai angin segar—film yang tidak hanya mengundang air mata, tetapi juga refleksi.
Sebuah karya yang menolak klise, menyiasati air mata, dan memilih untuk berbicara dengan kejujuran yang jarang kita temui di layar lebar.