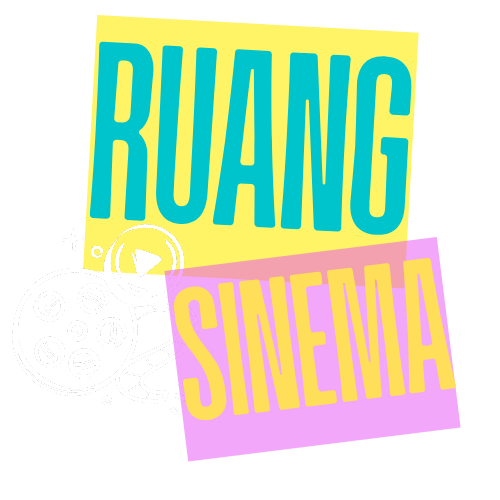Di tengah maraknya film keluarga yang menjual air mata secara instan, “Panggil Aku Ayah” tampil sebagai pengecualian yang layak disimak. Sebagai adaptasi dari film Korea “Pawn” (2020), karya produksi Visinema Pictures ini tidak sekadar menerjemahkan alur cerita, melainkan melakukan transformasi kultural yang cermat, menciptakan ulang kisahnya dalam konteks sosial, emosional, dan bahasa lokal Indonesia, tanpa kehilangan substansi dramatik nya.

Dengan premis yang sederhana, seorang anak kecil dijadikan jaminan utang oleh ibunya dan kemudian diasuh oleh dua penagih utang, film ini menawarkan potret alternatif mengenai keluarga, kasih sayang, dan kehadiran. Alih-alih menghadirkan konflik besar yang manipulatif, film ini justru menyusun kepedihan secara bertahap, lewat momen-momen kecil yang sangat manusiawi. Justru dari kesederhanaan inilah muncul kekuatan yang tidak dimiliki banyak film sejenis: emosi yang jujur.
Ringgo Agus Rahman dan Boris Bokir tampil di luar zona nyaman mereka. Ringgo, sebagai Dedi, menawarkan kompleksitas karakter yang kerap menahan gejolak emosinya dalam diam. Boris Bokir, yang biasanya diidentikkan dengan komedi, mengejutkan dengan gestur-gestur kehangatan yang subtil namun efektif. Namun pusat emosi film ini jelas terletak pada tokoh Intan kecil, diperankan oleh Myesha Lin. Tanpa harus membebani dirinya dengan narasi traumatik yang eksplisit, Myesha berhasil memanggil empati penonton hanya lewat cara ia memandang, diam, atau sekadar duduk tanpa bicara.
“Panggil Aku Ayah” adalah studi mengenai hubungan non-biologis yang dibangun atas dasar kehadiran dan pilihan. Dalam kebudayaan yang masih memuliakan garis darah sebagai penentu legitimasi keluarga, film ini secara halus mendekonstruksi gagasan tersebut. Kehangatan yang lahir antara Intan dan dua “ayah”-nya bukan ditentukan oleh ikatan genetik, melainkan oleh siapa yang memilih untuk tetap tinggal. Film ini tidak secara eksplisit menyerang nilai-nilai konvensional, namun cukup berani untuk merayakan keluarga sebagai institusi sosial yang lentur dan bisa dinegosiasikan.
Secara teknis, film ini bekerja dengan pendekatan visual yang cenderung minimalis, tapi fungsional. Sinematografi menghindari gaya yang mencolok, dan justru memilih untuk menempatkan kamera pada jarak yang intim. Medium shot dan close-up digunakan untuk menangkap ekspresi dan perubahan emosi dengan presisi, mengandalkan kekuatan akting alih-alih efek visual.
Penyutradaraan yang tenang dan tata musik yang tidak invasif menjadi kelebihan lain film ini. Musik latar hadir seperlunya, tidak pernah memaksa penonton untuk merasa sedih, melainkan hadir sebagai pelengkap atmosfer. Inilah yang menjadikan film ini lebih elegan dalam memperlakukan emosi: ia mempercayai penontonnya.
Meski demikian, film ini tidak bebas dari problem. Ketika cerita beralih ke fase Intan dewasa (Tissa Biani), terjadi penurunan intensitas emosi yang cukup signifikan. Pergeseran ini bukan semata karena performa akting, tapi karena struktur dramatik yang terlalu mengandalkan kilas balik dan memori, alih-alih membangun ketegangan baru. Transisi emosional dari masa kecil ke dewasa terasa lebih sebagai penutup administratif ketimbang ledakan dramatis yang menyempurnakan kisahnya.
Namun kekurangan ini tidak meniadakan pencapaian film secara keseluruhan. Justru melalui keterbatasannya, “Panggil Aku Ayah” memperlihatkan bahwa kekuatan sejati sebuah film tidak terletak pada besarnya konflik, tetapi pada kedalaman relasi dan konsistensi pendekatan naratifnya.
Lebih jauh, film ini layak diapresiasi karena tidak terjebak dalam eksotisme lokalitas. Bahasa Sunda yang digunakan tidak tampil sebagai gimmick kultural, tapi bagian integral dari relasi antar karakter. Pilihan-pilihan produksi ini menunjukkan kesadaran estetika yang tidak hanya berorientasi pasar, tapi juga menghargai keotentikan konteks sosial cerita.
“Panggil Aku Ayah” adalah film yang berdiri di tengah dua kutub: ia sentimental tapi tidak murahan, menyentuh tapi tidak manipulatif, sederhana tapi tidak dangkal. Ia bukan hanya tentang kasih antara orang tua dan anak, tapi tentang bagaimana manusia bertahan, saling menambal luka, dan membentuk ulang keluarga dari puing-puing keterasingan.
Dengan pendekatan naratif yang empatik, performa akting yang matang, dan sensitivitas sosial yang kuat, film ini menjadi salah satu karya yang layak dicatat sebagai kontribusi penting dalam lanskap sinema keluarga Indonesia kontemporer.