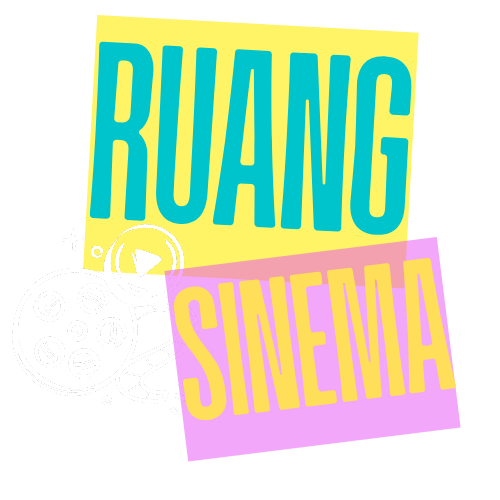Sebagai penutup dari salah satu waralaba horor paling populer dekade terakhir, The Conjuring: Last Rites seolah datang dengan beban ganda: menutup kisah panjang Ed dan Lorraine Warren dengan penuh perasaan, sekaligus mengingatkan publik mengapa seri ini pernah menjadi tolok ukur horor modern. Secara teori, tugas itu monumental. Dalam praktiknya? Hasilnya setengah matang, lebih layak disebut perpisahan sentimental ketimbang sebuah horor yang benar-benar hidup.
Mari kita mulai dengan yang positif. Film ini, pada momen-momen tertentu, masih mampu memanggil kembali atmosfer pekat yang dahulu membuat dua film pertama begitu menakutkan. Beberapa adegan tenang, pengelolaan ruang, serta keberanian memberi jeda senyap menjadi pengingat bahwa seri ini pernah menguasai bahasa horor dengan presisi. Di titik ini, kita bisa merasakan bayangan kehebatan lama.
Tidak bisa pula diabaikan kualitas akting Patrick Wilson dan Vera Farmiga. Seperti biasa, keduanya adalah jantung emosional dari saga ini. Wilson memberi Ed Warren dimensi rapuh namun kokoh, sementara Farmiga kembali menjadi pusat gravitasional narasi. Di tangan mereka, setiap adegan keluarga memiliki bobot yang lebih besar daripada sekadar “interupsi sentimental.” Inilah satu-satunya alasan mengapa film ini tidak runtuh total: karena chemistry dua aktor ini lebih kuat daripada naskah yang menopang mereka.
Namun sayangnya, segala hal positif itu segera dikubur oleh kelemahan mendasar: kelelahan formula. The Conjuring: Last Rites nyaris tidak menyimpan kejutan apa pun. Struktur jump scare dapat ditebak seperti jam dinding; ancaman visual lebih banyak terasa seperti gimmick; dan CGI yang kasar—terutama pada sosok Annabelle raksasa—malah mengundang tawa, bukannya teror. Alih-alih menggali kengerian, film ini tampak lebih sibuk memainkan sentimentalitas murahan, menjadikan horor sebagai latar belakang belaka untuk melodrama keluarga Warren.
Kehilangan James Wan di kursi sutradara semakin memperparah keadaan. Michael Chaves, yang berusaha keras meniru gaya Wan, justru memperlihatkan keterbatasannya. Alih-alih membangun ketegangan perlahan, ia mengandalkan kejutan instan, sehingga nuansa horor berubah menjadi parade trik klise. Ini bukan warisan; ini keletihan yang dipoles dengan lapisan nostalgia.
Lebih buruk lagi, beberapa bagian film mendekati komedi tak disengaja. Tragedi spiritual keluarga Warren, yang seharusnya menghantui, malah terkadang terasa seperti tontonan ringan. Bahkan momen yang dimaksudkan epik—seperti pertarungan final melawan kegelapan—jatuh datar, seakan sisa adegan superhero kelas B yang salah kamar. Jika The Conjuring pernah menjadi standar emas horor atmosferik, maka Last Rites hanyalah imitasi murahan yang lupa pada esensi ketakutan itu sendiri.
Akhirnya, film ini memang bisa disebut “penutup,” tetapi bukan dalam arti agung yang pantas diingat. Ia menutup saga dengan rasa setengah hati, menawarkan sekadar melodrama keluarga plus beberapa jump scare usang. Sebagai epilog, ia mungkin cukup fungsional. Sebagai horor, ia nyaris gagal total.
The Conjuring: Last Rites adalah bukti pahit bahwa bahkan waralaba sebesar ini pun tidak kebal terhadap kelelahan dan kehabisan ide. Farmiga dan Wilson berusaha keras menjaga bara tetap menyala, tetapi naskah dan penyutradaraan meredam setiap potensi api. Hasil akhirnya bukanlah teror, melainkan sentimentalitas yang dipaksa. Sebuah perpisahan, ya. Tapi perpisahan yang lebih terasa sebagai pengakuan bahwa kejayaan seri ini sudah lama terkubur.