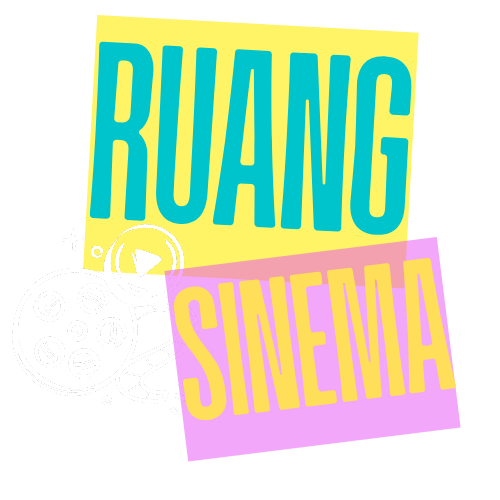Horor di Indonesia seperti tak pernah kehabisan stok hantu, tetapi justru sering kehabisan kedalaman. Pocong, kuntilanak, dukun, santet—semuanya sudah diperah sampai kering. Di tengah kejenuhan itu, Labinak: Mereka Ada di Sini datang membawa janji berbeda: bukan arwah gentayangan, melainkan keluarga kanibal yang menyamarkan ritualnya di balik yayasan pendidikan elite. Sebuah pilihan yang, setidaknya di awal, terdengar berani.
Namun, keberanian itu tak pernah menemukan bentuk. Film ini berdiri gagah dengan premis segar, lalu perlahan runtuh di bawah beban eksekusi yang terburu-buru. Alih-alih menyalakan obor baru bagi horor lokal, Labinak justru terjebak dalam kubangan ambisinya sendiri.
Naskah Rapuh, Cerita Tersendat
Kekuatan horor selalu ada pada cerita yang kokoh, tetapi Labinak justru mengabaikan hal paling mendasar itu. Keluarga Bhairawa, inti dari seluruh teror, diperlakukan seperti catatan kaki. Filosofi ritual kanibalisme mereka samar, motivasi mereka dangkal, dan sejarahnya hanya dilempar sepintas. Alih-alih menggali, film ini memilih berlari.
Akibatnya, narasi bergerak tersendat. Ketegangan yang seharusnya tumbuh organik malah berhenti di tengah jalan. Konflik datang terlalu cepat, lalu ditutup tergesa-gesa, tanpa konklusi yang memberi bobot. Klimaksnya lebih mirip pintu darurat yang dipaksa terbuka, bukan puncak yang dicapai dengan konsistensi.
Estetika yang Membuat Bising
Film ini sesungguhnya punya modal visual. Efek gore praktikal dikerjakan cukup rapi, tata artistik memadai, dan atmosfer awal menjanjikan. Namun modal itu dihambur-hamburkan. Scoring yang kelewat keras justru mengganggu, editing membuat ritme horor patah-patah, dan CGI kasar mencabut penonton dari imersi.
Teror bukan lahir dari suara keras, melainkan dari kesenyapan. Namun Labinak tampak tak percaya pada keheningan. Ia sibuk menjeritkan ketakutannya sendiri, sehingga yang tersisa di telinga penonton hanyalah kebisingan.
Akting yang Terjebak
Raihaanun memberi desperasi seorang ibu dengan intensitas memadai, sementara Nayla Denny menghadirkan energi segar. Tetapi akting sekuat apa pun akan sia-sia jika dibekap dialog kaku yang terdengar lebih seperti hafalan naskah ketimbang percakapan. Performanya akhirnya hanya menjadi lilin kecil yang terjebak dalam ruangan penuh asap.
Gimmick yang Menjatuhkan
Kesalahan paling fatal hadir di akhir film. Nama Sumanto—figur nyata yang pernah dihukum karena kasus kanibalisme—dimunculkan sebagai penutup. Keputusan ini bukan hanya murahan, tetapi juga menyalahi logika atmosfer yang sejak awal coba dibangun. Alih-alih mempertebal teror, gimmick itu merobohkan kredibilitas.
Sejak saat itu, Labinak berhenti menjadi horor. Ia menjelma parodi yang tak disengaja. Semua rasa gentar yang sempat tumbuh runtuh, berganti dengan gelak tawa getir. Keputusan ini menunjukkan kelemahan paling mendasar: kegagalan memahami di mana horor seharusnya berakhir.
Potensi yang Disia-siakan
Kanibalisme bukan sekadar horor biologis. Dalam sejarah budaya, ia sering dibaca sebagai metafora kerakusan, relasi kuasa, hingga kelaparan sosial yang tak pernah kenyang. Labinak punya peluang besar untuk menyalin tafsir itu: menjadikan keluarga Bhairawa simbol kelas dominan yang memangsa tubuh lemah. Namun peluang itu diabaikan. Yang tersisa hanyalah parade darah tanpa jiwa.
Inilah ironi terbesarnya: film yang seolah berani keluar jalur, justru gagal memberi makna. Alih-alih membuka pintu baru horor Indonesia, Labinak hanya menambah daftar panjang film yang mengandalkan sensasi sesaat.
Penutup: Ambisi yang Gagal
Labinak: Mereka Ada di Sini bukanlah tonggak baru, melainkan catatan kegagalan. Ia mengajarkan bahwa ide segar tak berarti apa-apa tanpa naskah yang kokoh dan disiplin artistik. Ia membuktikan bahwa gore dan suara keras tak bisa menggantikan rasa gentar yang sesungguhnya.
Film ini memang berbeda dari parade horor mistis yang memenuhi layar, tetapi perbedaan semacam ini tidak cukup. Ambisi besar yang dibawa Labinak hanya melahirkan tontonan yang kehilangan arah, lebih sibuk menakut-nakuti dirinya sendiri daripada penonton.
Horor sejati tidak pernah selesai di layar. Ia terus mengikuti penonton pulang, berbisik di kegelapan, dan menempel di kepala berhari-hari. Labinak tidak punya itu. Ia hanya punya kebisingan, gimmick murahan, dan jejak kecewa. Sebuah horor yang gagal, bukan karena kurang berani, melainkan karena tidak pernah tahu ke mana keberanian itu harus diarahkan.