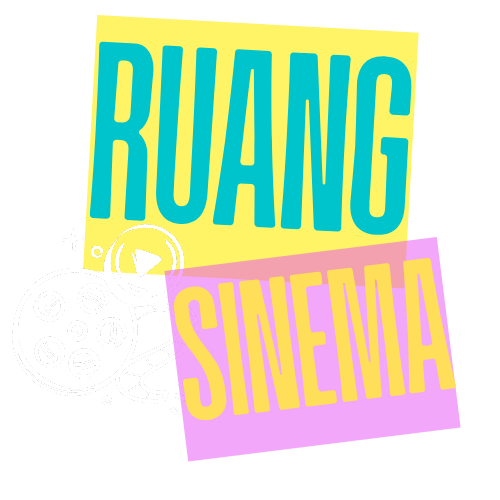Di tengah zaman ketika kata “edukasi seksual” masih jadi bisikan malu-malu, masyarakat Jawa tempo dulu justru pernah memiliki sistem yang—dengan caranya sendiri—cukup berani dan langsung: Gowok. Tradisi ini bukan dongeng, bukan pula kisah gelap yang dibisikkan di warung kopi. Ia nyata, terstruktur, dan pernah menjadi salah satu mekanisme pendidikan pranikah bagi laki-laki muda di Jawa.
Kini, lewat film “Gowok: Kamasutra Jawa” garapan Hanung Bramantyo, fragmen warisan budaya ini kembali mengemuka. Namun sebelum membahas filmnya, mari kita gali dulu apa itu sebenarnya Gowok.
Tradisi Edukasi “Hubungan Suami Istri” ala Jawa
Gowok merujuk pada perempuan dewasa (biasanya berusia 20–40 tahun) yang disewa oleh keluarga calon pengantin pria untuk mendidik anak mereka soal kehidupan rumah tangga—termasuk soal relasi seksual. Sebuah praktik yang hari ini mungkin akan dicap “liar”, tetapi di zamannya, justru dianggap wajar dan bahkan terhormat.

Edukasi ini tidak hanya soal tubuh dan gairah, tapi juga tata cara mengurus rumah, memasak, bersosialisasi, dan membentuk karakter seorang suami. Dalam banyak kasus, jika proses ini dianggap gagal, pihak keluarga bisa membatalkan pernikahan dan meminta kembali seserahan. Artinya, tanggung jawab gowok bukan main-main—ia adalah pelatih rumah tangga yang utuh.
Tak hanya nilai sosial, ada juga nilai ekonomis yang jelas: seorang gowok biasanya dibayar antara 0,25 hingga 0,35 gulden per hari. Di luar itu, ia akan diberi beras, kelapa, atau barang kebutuhan pokok sebagai tambahan. Dalam struktur ekonomi rakyat saat itu, ini adalah pendapatan yang layak. Gowok adalah pekerjaan, profesi, bukan sekadar relasi personal.
Tradisi ini diyakini mulai dikenal di wilayah Purworejo, Banyumas, dan sekitarnya sejak abad ke-15. Sejarahnya bahkan terkait dengan kedatangan armada Cheng Ho dari Tiongkok. Salah satu pengikutnya, perempuan bernama Goo Wok Niang, disebut sebagai pencetus awal model pendidikan ini, yang kemudian berkembang dan melebur dalam kebudayaan Jawa.
Dari Desa ke Festival Film Rotterdam
Masa keemasan gowok berlangsung hingga sekitar dekade 1960-an. Setelahnya, ia perlahan hilang: dikikis oleh interpretasi agama yang lebih ketat, norma-norma kesusilaan era Orde Baru, dan stigma moral masyarakat modern yang lebih suka sembunyi daripada membahas seksualitas secara terbuka.
Kini, tradisi ini hidup kembali—bukan di desa atau kampung, tapi di layar lebar. Film “Gowok: Kamasutra Jawa” yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduksi oleh Raam Punjabi (MVP Pictures) dijadwalkan tayang perdana pada 3 Februari 2025. Lebih dari itu, film ini telah masuk dalam kompetisi utama Big Screen di International Film Festival Rotterdam (IFFR) 2025.
Dengan latar waktu 1955–1965, film ini mengisahkan seorang gowok bernama Nyai Ratri (diperankan oleh Raihaanun), yang ditugaskan membimbing seorang pemuda, putra dari mantan kekasihnya. Dari relasi edukatif, cerita berkembang menjadi konfrontasi emosional, dendam, dan perenungan atas luka masa lalu.
Hanung menekankan bahwa film ini bukan eksploitasi erotisme, melainkan eksplorasi nilai dan etika: bagaimana peran suami-istri dibentuk oleh pengetahuan yang tak pernah diajarkan secara formal. “Ini tentang bagaimana kepuasan dalam hubungan suami istri berperan dalam menjaga harmoni rumah tangga,” ujar Hanung dalam wawancara dengan media.
Film ini juga diperankan sederet aktor papan atas, seperti Reza Rahadian, Raihaanun, Lola Amaria, Alika Jantinia, Devano Danendra, Khiva Rayanka, Nai Djenar Maisa Ayu, Ali Fikry, Donny Damara, dan Slamet Rahardjo.
Tradisi yang Layak Dibaca Ulang, Bukan Dihidupkan Mentah
Membaca kembali gowok bukan berarti menghidupkannya secara literal. Tapi ini adalah panggilan untuk mengenali bahwa pendidikan relasi bukan hal yang bisa diabaikan atau dianggap tabu. Masyarakat Jawa lama, dengan segala keterbatasan dan kontradiksinya, mencoba menjawab kebutuhan itu lewat caranya sendiri.
Tentu, praktik ini tak luput dari kontroversi: ada potensi eksploitasi, ada dominasi gender, dan ada ambiguitas relasi kuasa. Namun jika ditimbang secara adil, gowok juga menghadirkan gagasan bahwa relasi tidak cukup dibentuk oleh cinta dan moralitas semu—tapi oleh pemahaman yang konkret, pengalaman, dan kesiapan bertanggung jawab.
Hari ini, saat banyak orang masuk ke pernikahan hanya bermodal pesta dan akun Instagram bersama, barangkali kita bisa belajar dari keberanian masa lalu untuk bersikap jujur soal kebutuhan, peran, dan realitas dalam rumah tangga.