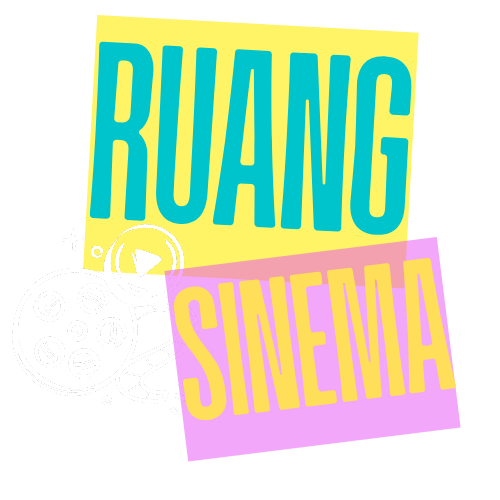Indonesia baru saja merayakan kemenangan manis lewat “Jumbo”, film animasi karya anak bangsa yang menggebrak dunia film animasi Indonesia dan membuat banyak orang sadar: kita ternyata bisa bikin animasi yang memukau, berkarakter, dan hidup. Namun, sebelum euforia itu sempat mendarah daging, muncullah “Merah Putih: One for All”, sebuah proyek animasi yang mengusung semangat kebangsaan, tapi malah memicu debat soal kualitas dan prioritas.
Alih-alih terasa sebagai “simfoni cinta negeri”, film ini lebih mirip mars wajib yang dinyanyikan tanpa perasaan, sekadar formalitas untuk memenuhi daftar hadir.

Perbandingan dengan “Jumbo” tidak bisa dihindari. “Jumbo” memikat lewat dunia yang detail, alur yang rapi, dan pesan yang meresap tanpa terasa menggurui. “Merah Putih: One for All” justru seperti brosur nasionalisme yang dianimasikan. Dialognya kaku, desain karakternya generik, dan ceritanya seperti disusun dengan template “ceramah motivasi 17 Agustusan” yang dipaksakan menjadi narasi film.
Bukan berarti film nasionalis harus membosankan. Lihat “Nusantara Rangers” atau “Battle of Surabaya”, keduanya menyuntikkan nilai cinta tanah air dengan kisah yang hidup, emosi yang mengalir, dan karakter yang punya jiwa. Sayangnya, “Merah Putih: One for all” memilih jalur aman: serba rapi di permukaan, tapi tanpa kedalaman.
Yang paling ironis, film ini muncul di saat publik sedang haus akan animasi Indonesia yang berani dan segar. Dengan momentum “Jumbo” yang sedang hangat, kesempatan emas terbuka lebar untuk menunjukkan bahwa animasi Indonesia tidak kalah kelas dari luar negeri. Namun, yang tersaji justru seperti pesan moral yang digoreng setengah matang—niatnya baik, tapi eksekusinya membuat penonton merasa sedang ikut apel pagi, bukan menikmati film.
Ketika cinta negeri disampaikan dengan cara yang justru menjauhkan orang dari rasa memiliki itu sendiri. Nasionalisme di layar lebar seharusnya menggugah, bukan sekadar mengingatkan bahwa “kita harus bangga”. Karena jika harus diingatkan terus-menerus dengan cara ini, pertanyaannya adalah: benarkah kebanggaan itu pernah tumbuh, atau hanya menjadi slogan yang diulang tanpa makna?
“Merah Putih: One for All” bisa saja menjadi titik balik jika berani keluar dari pola kampanye visual yang terlalu aman. Tapi selama pendekatannya masih sebatas menandai checklist “film nasionalis” demi laporan pertanggungjawaban, maka hasilnya akan selalu terasa seperti proyek tugas sekolah—lengkap dengan presentasi PowerPoint, bukan karya seni yang lahir dari gairah.
Karena pada akhirnya, pertanyaan yang paling mengusik bukan sekadar “Apakah film ini layak tonton?”, melainkan “Mengapa kita rela mengeluarkan dana publik untuk hasil yang tak sepadan?” Cinta negeri memang tak ternilai, tapi biaya produksinya jelas ada angka di laporan. Dan setiap rupiah yang dikeluarkan seharusnya berbuah sesuatu yang membuat publik tersentuh, bukan hanya tersadar bahwa uang mereka dipakai untuk menayangkan animasi yang layaknya bisa diselesaikan di ruang komputer sekolah. Nasionalisme bukan perkara seberapa sering ia diucapkan, melainkan seberapa dalam ia bisa dirasakan—dan “Merah Putih: One for All” sayangnya belum sampai ke sana.