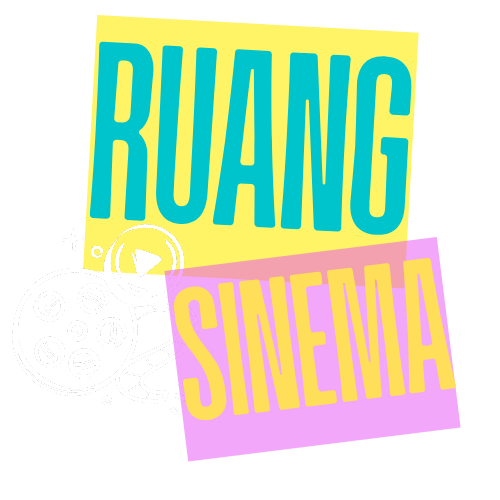Ada satu ambisi besar yang dibawa Garin Nugroho dalam film Siapa Dia : menjadikan film sebagai surat cinta kepada sinema Indonesia. Sebuah ambisi yang, di atas kertas, terdengar begitu menjanjikan. Menggabungkan musikal, lintasan sejarah, dan kisah cinta lintas generasi, film ini seolah ditakdirkan menjadi ode puitis bagi perjalanan panjang layar perak Nusantara. Namun ketika film akhirnya tayang, kenyataan justru menunjukkan sesuatu yang berbeda: ambisi megah itu runtuh dalam eksekusi yang gamang, serba tanggung, dan pada titik tertentu, nyaris gagal sepenuhnya.
Sejak adegan pembuka, tanda-tanda ketidakmatangan sudah terasa. Judul film ditampilkan dengan desain yang menyerupai klip art murahan, lebih dekat dengan presentasi amatir ketimbang karya sinematis. Sebuah detail yang mungkin remeh, namun dalam sinema, detail adalah pernyataan. Alih-alih memberi kesan agung, Siapa Dia langsung menjerumuskan dirinya ke dalam kesan produksi seadanya.
Narasi film dibagi ke dalam babak-babak, masing-masing mewakili era berbeda dari garis keturunan Layar—buyut, kakek, ayah, hingga sang tokoh utama. Secara konseptual, pola ini menjanjikan kerangka yang kokoh, sebuah perjalanan lintas zaman yang bisa merekam denyut sejarah perfilman Indonesia. Namun dalam praktiknya, alur terasa tergesa-gesa, lompat-lompat, dan hampa emosi. Hubungan antar karakter tak pernah tumbuh utuh; sebelum ada ruang untuk membangun keintiman, cerita sudah berpindah, atau karakter dibiarkan mati begitu saja. Kisah cinta yang seharusnya menjadi urat nadi musikal ini justru tumpul, terfragmentasi, dan tanpa resonansi emosional.
Yang lebih problematis, film ini terjebak dalam male gaze yang telanjang. Perempuan hadir semata sebagai objek orbit, sebagai latar dari kegelisahan eksistensial sang tokoh pria. Mereka tak diberi agensi, tak memiliki jalan cerita sendiri, sekadar menjadi medium untuk menegaskan perjalanan batin lelaki. Alih-alih merayakan sejarah sinema Indonesia—yang penuh dengan kontribusi perempuan penting—film ini justru terjebak dalam pandangan reduktif yang mengulang pola patriarki lama.
Secara teknis, kelemahan film semakin kentara. Kamera bergerak kaku, membiarkan adegan musikal terjebak dalam statisitas yang melelahkan. Padahal musikal adalah genre yang menuntut kelincahan visual, integrasi mulus antara musik, tarian, dan sinematografi. Di sini, kamera lebih sering menjadi saksi pasif ketimbang partisipan aktif, sehingga lagu-lagu yang dinyanyikan hanya terasa sebagai selingan, bukan bagian organik dari narasi. Transisi antar-lagu dan adegan juga kerap patah, meninggalkan kesan kasar dan tidak terjembatani.
Editing pun bermasalah. Ritme film kehilangan kendali; seolah ada kewajiban untuk menyelipkan nyanyian setiap dua menit, tanpa mempertimbangkan logika dramatik. Alur menjadi repetitif, hingga bukannya mengikat dalam emosi, film justru mengundang rasa jenuh. Sejumlah elemen artistik—seperti tata busana dan color grading—memang layak dicatat. Wardrobe tampil penuh respek pada sejarah mode, dan palet warna kerap memberi kesan elegan. Namun pencapaian visual ini tak cukup untuk menutupi keroposnya struktur utama.
Yang paling menyedihkan, film ini gagal menegakkan dirinya sebagai karya Garin Nugroho. Nama Garin identik dengan kepekaan visual, keberanian eksperimental, dan kekuatan puitis yang khas. Tetapi dalam Siapa Dia, kehadiran itu seakan menguap. Film terasa mentah, seperti draf awal yang belum disentuh tangan penyair sinema. Bahkan dibanding eksperimen terdahulu Garin yang sering membelah opini, Siapa Dia berdiri di titik terendah: bukan provokasi artistik, melainkan kebingungan kreatif.
Ada kilasan keindahan yang sesekali muncul—setelan kostum yang indah, atau palet warna yang menawan—namun itu tidak lebih dari kilau kosmetik di atas tubuh narasi yang rapuh. Untuk sebuah film yang mengklaim diri sebagai surat cinta bagi sinema Indonesia, pencapaian semacam ini jelas tidak memadai. Cinta sejati kepada sinema seharusnya lahir dari penghormatan pada narasi, pada kedalaman karakter, pada pertemuan organik antara gambar dan musik. Siapa Dia justru memperlakukan elemen-elemen itu sebagai ornamen tempelan, yang akhirnya membuat film tampak seperti pameran museum yang membosankan, bukan sebuah pengalaman sinematis yang hidup.
Pada akhirnya, Siapa Dia adalah contoh gamblang dari bagaimana ambisi besar bisa runtuh karena kerapuhan detail. Ia ingin menjadi puisi panjang tentang cinta dan sejarah, tetapi yang lahir justru kolase patah-patah yang tak kunjung menyatu. Sebagai kritik, saya melihat film ini bukan sekadar karya yang gagal, melainkan alarm keras tentang bahaya artistik ketika visi dan eksekusi berjalan di jalur yang terpisah.
Jika benar film ini dimaksudkan sebagai surat cinta untuk sinema Indonesia, maka sayangnya, cinta itu tak pernah tiba. Yang tertinggal hanyalah sebuah draft: penuh janji, namun tanpa roh.