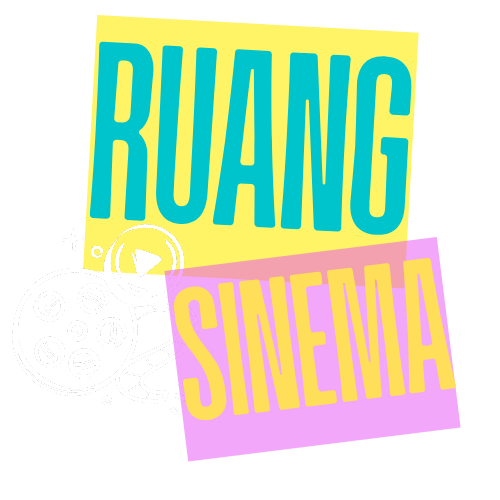Di negeri yang tanahnya menyimpan begitu banyak kisah kematian dan arwah penasaran, Panggilan dari Kubur seharusnya menjadi panggung emas bagi pocong untuk kembali menakuti. Sayangnya, sosok ini justru terpinggirkan, menjadi cameo di filmnya sendiri—bukti bahwa industri kita kadang tak tahu cara menghormati ikon yang diwariskan budaya.
Sinema horor Indonesia lahir dari tanah yang gemuk oleh mitos, legenda, dan cerita turun-temurun. Kita punya hutan penuh beringin tua tempat suara-suara tak kasat mata bersembunyi, punya sungai yang riak arusnya mengisyaratkan tragedi, punya kuburan di pinggir desa yang jadi bagian ingatan kolektif. Dengan modal budaya sebesar itu, mestinya horor kita bisa tumbuh subur dan menjulang tinggi. Namun, sering kali yang tumbuh justru benalu—film yang meminjam kulit mitos tapi mengisinya dengan daging klise.
Panggilan dari Kubur adalah salah satu benalu itu. Bukan berarti ia tak punya pesona. Premisnya menggoda: kutukan turun-temurun, drama hubungan ibu-anak yang jarang disentuh horor arus utama, dan kembalinya Nirina Zubir ke genre horor yang selalu haus ikon baru. Bahkan ada pocong—sosok yang, bila digarap dengan penghormatan budaya dan keberanian artistik, bisa menjadi figur horor modern yang legendaris. Namun, harapan itu cepat mengering seperti tanah yang belum sempat disiram.
Film memulai langkah dengan nada sendu. Drama pembuka menjanjikan kedalaman emosional—narasi yang mencoba memeluk penonton, bukan sekadar menampar mereka dengan jump scare. Tapi pelukan itu berlangsung terlalu lama, berubah jadi canggung. Begitu tragedi tenggelamnya sang anak terjadi, film yang tadinya berjalan pelan mendadak berlari seperti seseorang yang baru sadar kereta terakhir hampir berangkat. Adegan horor datang bertubi-tubi, saling tabrak, kehilangan irama, dan menumpuk seperti mimpi buruk yang disatukan tanpa logika tidur.
Sosok pocong di sini menjadi korban terburuk dari ketergesaan itu. Ia hadir bukan sebagai mitos yang berlapis, melainkan sekadar pemicu rasa kaget sesaat. Tidak ada upaya menanamkan rasa gentar yang melekat setelah lampu bioskop menyala. Padahal, dalam budaya kita, pocong adalah simbol jiwa yang terperangkap di antara dunia hidup dan mati—ikon yang bisa menggedor rasa takut sekaligus memancing empati. Mengabaikan kedalaman simbol itu sama saja seperti mengabaikan sejarahnya.
Naskah Baskoro Adi sebenarnya rapi dalam kerangka, tapi tipis di isi—seperti rumah megah dengan ruang tamu kosong. Build-up teror nyaris tak pernah mencapai puncak. Setiap kali ketegangan mulai terbentuk, film justru memutuskannya, seolah takut penonton terlalu lama menahan napas. Ini bukan sekadar kelemahan teknis; ini cermin mentalitas industri yang khawatir keluar dari zona aman.
Di ranah teknis, ada satu sisi yang patut dipuji: sinematografi. Cahaya temaram, bingkai yang menciptakan rasa terperangkap, dan keheningan yang kadang efektif. Namun musik dan penyuntingan justru merusak pondasi itu. Scoring terdengar seperti musik sinetron sore, atau—lebih buruk lagi—mengandalkan letupan volume untuk memaksa penonton terkejut. Editing terasa terburu-buru; transisi tak mulus, beberapa adegan horor kehilangan tenaga karena pemotongan yang salah momentum.
Para aktor bekerja dengan bahan baku terbatas. Nirina Zubir dan Nugie tampil aman, sesekali memberi nyawa pada adegan yang nyaris runtuh. Tapi aktor pendukung dibiarkan mengisi ruang kosong tanpa peran berarti. Dialog mereka dangkal, tak memberi peluang lahirnya interpretasi atau misteri.
Dan seperti horor lokal lainnya, film ini kehilangan arah di babak akhir. Alih-alih klimaks yang memuncak, ia menutup cerita dengan tergesa—seperti pembawa acara yang lupa menyiapkan kalimat penutup. Lebih buruk lagi, ada ide yang jatuh ke ranah absurditas tanpa sadar: seorang anak kecil menjadi pocong untuk menakut-nakuti ibu hamil. Sebuah konsep yang, jika disadari potensinya sebagai satire gelap, bisa memancing perdebatan; tapi di sini, ia hanya mengundang tawa yang tak diundang.
Di luar layar, Panggilan dari Kubur berbicara banyak tentang industri kita. Ia menunjukkan bagaimana film dengan premis kaya bisa dikebiri oleh rasa takut mengambil risiko. Bagaimana mitos lokal, alih-alih diperlakukan sebagai warisan, malah jadi tempelan estetika. Dan bagaimana horor kita sering lupa bahwa ketakutan paling efektif datang dari bayangan yang mengikuti kita bahkan setelah cerita berakhir.
Akhirnya, film ini memang memanggil. Tetapi panggilan itu tak menggema lama. Ia tenggelam di antara suara-suara lain yang lebih berani, lebih jujur, dan lebih percaya pada potensi horor sebagai seni, bukan sekadar produk. Di situlah letak ironi terbesar Panggilan dari Kubur: ia adalah kisah tentang arwah yang terjebak di antara dunia, namun filmnya sendiri terjebak di antara visi dan eksekusi—tak pernah benar-benar menjadi salah satunya.