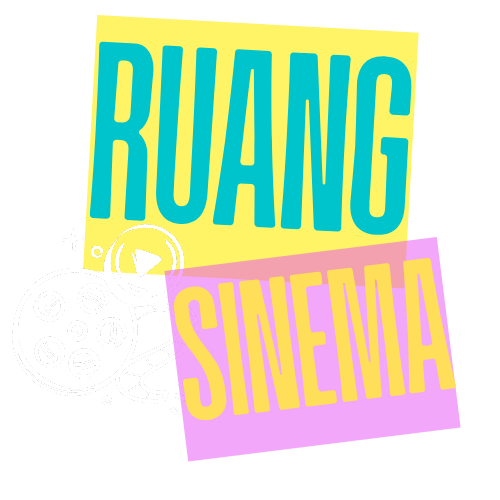Di tangan sineas yang berani dan bermoral, film perang bisa menjadi medan paling jujur untuk menggugat kekuasaan, menyingkap luka sejarah, dan merayakan kemanusiaan. Tapi “Believe: The Ultimate Battle” memilih jalan berbeda—jalan yang lebih nyaman dan jauh dari risiko: menjadi propaganda yang dibungkus sinematik mulus, namun minim keberanian naratif. Ini bukan film perang. Ini adalah surat cinta untuk institusi berseragam, dikirim lewat pos kilat bernama industri hiburan.
Film ini mencoba menarasikan perjalanan Agus Subianto—dari anak berandal yang dibentuk disiplin militer, hingga menjelma menjadi panglima pasukan elit TNI. Tapi alih-alih menjadi studi karakter yang dalam, film ini berubah menjadi video motivasi berdurasi dua jam: penuh adegan heroik, karakter tanpa konflik batin, dan musuh yang didesain hanya untuk dimusnahkan. Tak ada ruang abu-abu, tak ada keraguan, tak ada dosa. Semua tertata rapi seperti barisan upacara bendera.

Pertanyaannya sederhana: mengapa harus seperti ini? Mengapa setiap film yang menyentuh sejarah militer Indonesia selalu terjebak dalam glorifikasi? “Believe” punya semua perangkat untuk menjadi karya yang lebih bermakna—anggaran yang jelas besar, kru teknis yang kompeten, hingga aktor yang mampu tampil meyakinkan. Tapi semua itu diboroskan untuk satu hal: membangun mitos seorang prajurit ideal, alih-alih menggali kompleksitas manusia di tengah konflik.
Dari sisi produksi, memang sulit membantah bahwa film ini unggul. Koreografi pertempuran terasa realistis, sinematografi digarap serius, dan tata suara menyatu apik dengan suasana medan tempur. Tapi sebagus apapun teknisnya, semua menjadi sia-sia jika tidak didukung naskah yang jujur. Seperti lukisan indah dari pertempuran imajiner, tapi semua darahnya terbuat dari cat merah dan semua tangisan hanya rekayasa panggung. Emosi dihadirkan sekadar formalitas.
Yang paling menjengkelkan adalah cara film ini mereduksi konflik Timor Timur. Fretilin digambarkan secara simplistik sebagai teroris haus darah tanpa motivasi ideologis. Tak ada latar sosial, tak ada penjelasan sejarah, tak ada percikan kemanusiaan. Mereka hanya muncul untuk ditembak, dipukul, lalu dilupakan. Bahkan film superhero pun memberikan villain-nya setidaknya satu alasan logis. “Believe” tak repot-repot sejauh itu. Buat apa? Toh penonton akan bertepuk tangan melihat pasukan elite menyerbu dan menang.
Lebih jauh, film ini memilih untuk mengabaikan narasi yang telah dibangun oleh berbagai laporan internasional—bahwa operasi militer di Timor Timur bukan sekadar “misi penyelamatan”, tetapi bagian dari pelanggaran HAM sistemik. Tapi “Believe” tidak tertarik menyentuh itu. Film ini bahkan tidak menyentuh bagaimana dilema moral atau trauma membentuk sosok Agus. Yang ditampilkan hanya semangat baja, ketegasan tanpa kompromi, dan patriotisme yang dipoles hingga mengilap. Ini bukan potret manusia, tapi katalog poster motivasi.
Dan jangan harap ada representasi perempuan yang berarti di sini. Istri Agus hanya menjadi properti naratif, karakter yang muncul untuk mendukung sang suami tanpa diberi kedalaman. Bahkan ketika sempat disinggung bahwa sang istri sempat ragu menerima lamaran karena konflik cita-cita, film buru-buru melompat. Dialog dangkal seperti “Halo Dek” menghapus kesempatan untuk menjelajah relasi yang lebih emosional. Hasilnya, perempuan dalam film ini hanya pelengkap, bukan manusia utuh.
Satu-satunya momen jujur dari film ini adalah betapa telanjangnya niat propaganda itu sendiri. Semua elemen cerita bergerak untuk satu tujuan: memahat figur Agus Subianto sebagai ikon militerisme modern. Dan jika itu memang tujuannya, maka “Believe” sukses besar. Ini film yang bisa membuat generasi muda memimpikan sepatu lars dan seragam loreng. Tapi jika kita bicara tentang film sebagai medium pencarian kebenaran, sebagai cermin kritis atas sejarah dan kekuasaan, maka “Believe” gagal total.
Film ini tidak merayakan patriotisme, tapi memonopoli maknanya. Ia tidak memberi ruang bagi suara-suara korban, tidak memberi tempat bagi keraguan atau kegagalan. Semua harus sempurna, karena hanya dalam kesempurnaan itulah propaganda bekerja. Dan di saat dunia semakin jujur merekonstruksi masa lalunya, Indonesia justru memilih membuat film yang mundur ke belakang: ke era di mana negara selalu benar, dan rakyat cukup menjadi penonton yang bangga.
Jika “Believe” adalah gambaran masa depan film perang Indonesia, maka kita sedang melangkah menuju industri sinema yang dibungkam oleh kepentingan. Sebuah sinema yang berani secara visual, tapi takut secara moral. Dan dalam lanskap semacam itu, kemenangan bukan milik mereka yang paling megah, tapi mereka yang paling tunduk.