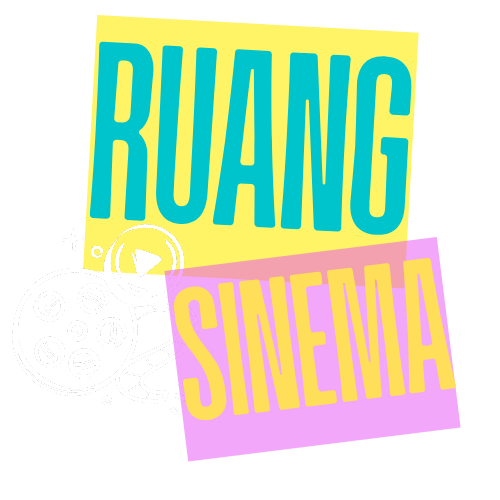Sudah waktunya kita jujur: sebagian besar film horor Indonesia tidak menakutkan—mereka hanya berisik. Dan ‘Kampung Jabang Mayit: Ritual Maut‘ membuktikan bahwa ketakutan bisa dijual, bahkan tanpa isi, selama dibungkus dengan mitos, latar kampung terpencil, dan sesosok dukun perempuan berwajah masam.
Diadaptasi dari utas viral 2022 dan podcast populer yang katanya “ditonton 20 juta kali”, film ini terlalu sibuk memamerkan sumbernya ketimbang menyusun ulang narasi yang layak untuk layar lebar. Ia berjalan seperti konten YouTube yang dipanjangkan paksa, dengan logika cerita yang tambal-sulam, pengembangan karakter yang dangkal, dan gaya visual yang lebih cocok jadi latar

Premisnya sebenarnya menjanjikan: Weda (Ersya Aurelia), model muda yang hamil di luar nikah, dibawa ke desa asal kekasihnya, Bagas (Bukie B. Mansyur), bernama Rangkaspuna. Di sana, mereka terseret dalam ritual pagan sadis yang dipimpin dukun bernama Ni Itoh (Atiqah Hasiholan). Tapi janji tinggal janji, karena yang tersaji adalah parade kejutan murahan (cheap thrills) dan simbolisme palsu yang tidak pernah sampai ke akar persoalan.
Film ini mencoba bermain di ranah folk horror, genre yang mengandalkan atmosfer ketidaknyamanan, kebudayaan lokal, dan ritus kuno. Tapi alih-alih terasa menyeramkan, ‘Kampung Jabang Mayit‘ lebih seperti tur kebudayaan gelap versi sinetron malam Jumat: banyak jargon mistik, sedikit logika. Visual patung kesuburan dan tetua kultus yang seharusnya memancing refleksi, justru tampil seperti properti pameran cosplay—kosong makna, penuh gaya.
Lebih parah lagi, film ini terjebak dalam dua kutub yang tak pernah menyatu: eksploitasi tubuh perempuan dan niat setengah hati untuk mengkritiknya. Weda, sebagai protagonis, tidak diberi ruang untuk berkembang sebagai manusia. Ia adalah simbol pasif—digiring, dikorbankan, dan direduksi menjadi rahim berjalan. Jika ini dimaksudkan sebagai kritik atas patriarki dan kekerasan berbasis adat, maka ia gagal total karena tidak pernah memberi Weda agensi. Yang ada hanyalah penderitaan demi penderitaan yang dimanipulasi demi sensasi.
Pacing film pun tak konsisten: babak pertama berjalan lambat seolah ingin jadi film art-house, tapi masuk paruh kedua, film berubah jadi tontonan jebakan jumpscare yang seolah wajib muncul setiap lima belas menit. Dan semuanya datang dengan efek suara yang overdramatis, seperti menyaksikan sinetron horor dengan volume maksimal. Ketegangan tidak dibangun—ia dipaksakan.
Akting para pemerannya pun terbagi dua: yang terlalu menahan, dan yang terlalu berlebihan. Ersya Aurelia tampil seperti korban iklan shampoo yang kebingungan, Bukie B. Mansyur tidak lebih dari tokoh cowok bermasalah dengan moral yang membingungkan, dan satu-satunya yang menyisakan impresi adalah Atiqah Hasiholan—itu pun bukan karena penokohan yang kuat, tapi karena ia satu-satunya yang tampak benar-benar ingin memerankan karakternya dengan serius.
Namun masalah paling mencolok dari ‘Kampung Jabang Mayit‘ bukan teknis, bukan akting, bahkan bukan ritus sesatnya—melainkan kemalasan berpikir di baliknya. Film ini merasa cukup hanya dengan menampilkan lokalitas sebagai eksotisme. Seolah-olah, selama desa terpencil dan kepercayaan kuno dimunculkan, maka otomatis film itu akan terasa otentik dan ‘berbudaya’. Ini adalah bentuk kemalasan intelektual yang sayangnya masih terlalu sering terjadi dalam film horor Indonesia.
Ketimbang menggali psikologi ketakutan, atau menyoal bagaimana tradisi bisa berubah jadi alat represi, film ini malah sibuk menggampangkan semuanya dalam narasi hitam-putih. Ni Itoh jahat, Weda korban, Bagas pengecut, dan penonton diminta menelan itu semua tanpa diberi ruang berpikir. Ia menjual mitos, tapi takut menyentuh politik tubuh. Ia memanfaatkan horor, tapi tak pernah berani bertanya: siapa yang paling diuntungkan oleh rasa takut?
Dan di sinilah letak ironi paling pahit: film ini, yang konon lahir dari keresahan budaya dan cerita rakyat, justru memperkuat budaya yang sama yang dulu mengorbankan perempuan atas nama adat. Ini bukan subversi, ini konservatisme yang disamarkan sebagai progresivitas.
“Kampung Jabang Mayit: Ritual Maut” adalah contoh sempurna bahwa popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Ia mungkin memuaskan penonton awam yang menginginkan horor cepat saji, tapi sebagai karya sinema—lebih-lebih sebagai cerminan kritik sosial—film ini tak punya nyali, tak punya gagasan, dan tak punya arah. Ia hanya parade kekerasan simbolik yang dibungkus rapi dengan kemasan pseudo-feminisme dan bumbu lokalitas.
Jika horor seharusnya membuat kita tidak nyaman karena menyentuh hal-hal yang tabu, maka film ini hanya berhasil membuat kita tidak nyaman karena miskin gagasan. Saat horor hanya jadi gimmick, dan tubuh perempuan jadi umpan utama, apa bedanya film ini dengan tontonan eksploitatif lainnya?
Dan jika ini disebut representasi horor modern Indonesia, maka mungkin yang paling menakutkan bukan setannya—tapi kegagalan kita membedakan antara ketakutan dan kebisingan.