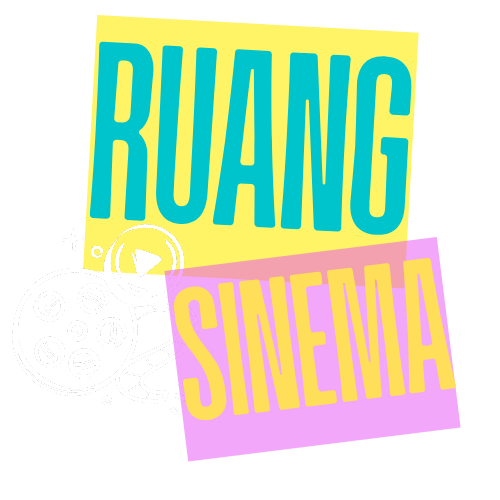Di tengah semangat baru sinema Indonesia yang mulai mengeksplorasi bentuk, tema, dan bahasa, “GJLS: Ibuku Ibu-Ibu” justru hadir sebagai antitesis menyakitkan dari perkembangan itu. Bukan karena ia subversif. Bukan karena ia menawarkan wacana liar yang memancing dialog. Tapi karena ia malas. Sungguh malas.
Film ini tidak menyodorkan apa-apa selain parade kelucuan murahan yang dibungkus seolah “absurd”, padahal sejatinya hanya sampah verbal dan visual yang dijejalkan ke layar dengan keyakinan bahwa “penonton akan tertawa kok”. Dan ya, sebagian memang tertawa. Tapi apa yang ditertawakan?
Mulai dari awal film, kita sudah disambut dengan lelucon yang menjadikan tubuh perempuan sebagai obyek — bukan hanya obyek cerita, tapi obyek seksualitas dan objek ejekan. Tak lama kemudian muncul karakter penyandang disabilitas, yang sayangnya hanya difungsikan sebagai pengganggu situasi dan pemancing tawa. Dalam dunia GJLS, tubuh-tubuh yang berbeda, yang rentan, yang marjinal — tidak dihadirkan untuk dipahami, tapi untuk ditertawakan. Mereka tidak diberi ruang bicara, hanya diberi tempat sebagai target kekonyolan.
Lucu? Tidak.
Lelucon yang berulang tentang masturbasi, desahan perempuan, ejekan terhadap orang miskin, hingga penyebutan “anak goblok” sebagai punchline — semuanya dibiarkan bergulir tanpa sedikit pun konteks yang memperlihatkan bahwa ini sekadar hiperbola atau sindiran. Tidak ada. Yang ada justru glorifikasi atas kekerasan simbolik itu sendiri.
Dan ketika ada yang mencoba membela film ini sebagai “satire”, sebagai “komedi absurd”, saya hanya bisa bertanya: di mana absurditasnya? Di mana satirnya? Satire menertawakan kuasa, bukan menertawakan yang tak berdaya. Absurd bukan berarti boleh semena-mena. Ketika kekerasan verbal dijadikan tawa tanpa narasi yang jelas, itu bukan satire — itu hanya pelecehan yang memakai topeng kelucuan.
Yang paling ironis adalah keberadaan bloopers di akhir film. Mungkin dimaksudkan sebagai pemanis penutup, tapi justru menjadi puncak dari betapa film ini tidak sadar pada luka yang ia buat. Lelucon seksisme diulang lagi, penghinaan terhadap karakter disabilitas ditegaskan ulang, dan semua itu dibingkai dalam suasana tawa dan keakraban. Seolah kita diajak berkata: “Gak apa-apa kok, kan cuma bercanda.”
Masalahnya, bercandanya menyakiti.
Bukan hanya menyakiti karakter dalam film, tapi menyakiti kita semua yang berharap sinema bisa menjadi ruang yang cerdas dan manusiawi. Menonton “GJLS: Ibuku Ibu-Ibu” seperti menyaksikan sekelompok orang yang yakin bahwa budaya populer adalah milik mereka semata — dan karena itu mereka bebas menertawakan siapa saja, menjadikan tubuh siapa pun sebagai bahan olok-olok, lalu menamainya “komedi tanpa batas”.
Saya tidak sedang menulis ini karena ingin mencari moralitas dari sebuah film komedi. Saya menulis ini karena film ini secara terang-terangan menunjukkan bahwa sebagian dari kita masih merasa tawa bisa membenarkan segalanya. Padahal tawa, ketika kehilangan empati, bisa lebih tajam dari hinaan.
Dan ketika film ini mencoba menyisipkan semacam “pesan” di ujung — bahwa ada karma, bahwa karakter bisa berubah — semuanya terasa seperti formalitas. Tak ada jejak yang cukup kuat untuk membuat kita percaya pada transformasi itu. Bagaimana bisa penebusan terjadi setelah satu jam lebih film ini menyiram penonton dengan kekerasan simbolik tanpa henti?
Film ini bisa jadi akan tetap laku. Tiketnya mungkin tetap terjual habis. Tapi itu bukan ukuran kualitas, apalagi keberanian. Yang ramai belum tentu penting. Yang laku belum tentu layak. Dan “GJLS: Ibuku Ibu-Ibu” adalah pengingat bahwa popularitas bukan jaminan kepantasan.
Komedi adalah genre yang sulit, karena ia butuh kecerdasan — bukan hanya dalam menulis punchline, tapi dalam membaca kenyataan. Ia harus tahu siapa yang ditertawakan, dan kenapa. Komedi yang jahat bukan hanya menyasar, tapi juga membiarkan penonton merasa bahwa kekejaman itu normal. Bahwa tidak apa-apa mengolok-olok difabel. Tidak apa-apa menjadikan perempuan sebagai suara latar untuk masturbasi. Tidak apa-apa menyebut anak miskin sebagai “goblok”. Karena ini “cuma film komedi”.
Tapi tidak. Ini bukan “cuma”. Ini adalah gambaran bagaimana tawa bisa dipelintir menjadi senjata yang membenarkan ketimpangan. Dan selama kita masih tertawa atas penderitaan yang lain, kita sedang menunda kemajuan. Kita sedang menyeret budaya pop kita mundur ke jurang dangkal yang menertawakan luka sebagai hiburan.
“GJLS: Ibuku Ibu-Ibu” bukan film buruk karena teknis. Tapi karena secara sadar memilih untuk tidak peduli. Dan di zaman seperti sekarang, ketidakpedulian adalah bentuk paling parah dari kemunduran.