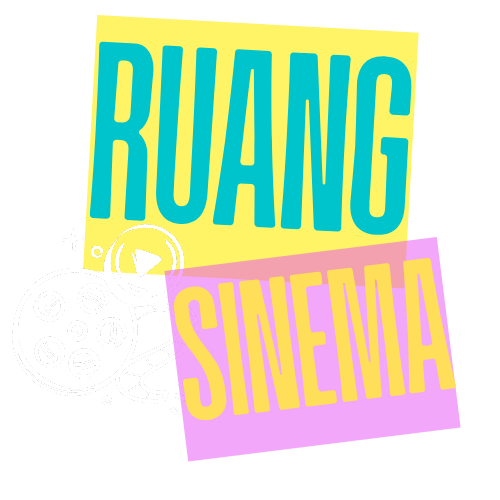Ada film yang hanya menepuk pundak kita, sekadar lewat, lalu hilang tertelan deru bioskop dan bau mentega popcorn. Tapi ada juga film yang datang seperti seseorang yang dulu pernah kita kenal: menghampiri pelan-pelan, menggandeng tangan, lalu memaksa kita duduk dan bercermin. Sore: Istri dari Masa Depan adalah yang kedua—dan dalam lanskap film Indonesia yang kian didominasi oleh horor-horor instan, ia hadir sebagai anomali yang membahagiakan.
Disutradarai oleh Yandy Laurens, sineas yang tak pernah tergesa-gesa tapi selalu tepat sasaran, film ini membawa kita pada kisah cinta, kehilangan, dan trauma, tanpa perlu berteriak-teriak soal cinta, kehilangan, dan trauma. Ia seperti surat panjang yang ditulis dengan hati-hati dan perasaan penuh: menyakitkan, tapi mengandung penghiburan.
Dari permukaan, premisnya mungkin terdengar familiar—tentang seorang perempuan bernama Sore (Sheila Dara) yang terjebak dalam time-loop, berulang kali mencoba menyelamatkan pasangannya, Jonathan (Dion Wiyoko), dari masa depan yang tragis. Tapi ini bukan Edge of Tomorrow, bukan pula Tenet. Yandy Laurens tidak tertarik pada kejar-kejaran logika dan kepuasan plot twist. Ia menggunakan time-loop bukan sebagai gimmick, melainkan sebagai metafora tentang cinta yang keras kepala, luka yang membentuk kita, dan pahitnya kenyataan bahwa tak semua hal bisa diperbaiki—bahkan oleh cinta yang paling tulus sekalipun.
Dalam dunia perfilman, especially di Indonesia, time-loop sering jadi perangkat naratif yang salah urus. Entah dijadikan alat untuk menjebak tokoh-tokoh dalam labirin cerita yang membingungkan, atau dipakai semata sebagai penarik tontonan. Tapi Yandy Laurens tahu betul: yang membuat penonton bertahan bukan kerumitan struktur, melainkan kejujuran emosi. Dan Sore: Istri dari Masa Depan dibangun sepenuhnya di atas fondasi emosi itu—bukan pamer logika, bukan permainan visual semata.
Film ini cerdas tanpa harus cerewet, menyayat tanpa harus cengeng. Yandy menyiapkan panggung yang detail: visual yang seperti lukisan, Kroasia yang dingin sekaligus hangat, aurora yang melapisi trauma, senja yang menjadi simbol luka dan harapan. Color grading yang matang, sinematografi yang intim, serta music scoring yang selalu hadir di saat paling tepat—membuat film ini terasa seperti karya yang disusun bukan cuma dengan otak, tapi juga dengan jiwa.
Berbicara soal visual, film ini dengan jujur adalah salah satu yang paling indah secara sinematik dalam lanskap film Indonesia belakangan ini. Dari Kroasia yang dingin dan sunyi hingga pencahayaan senja yang muram tapi hangat, setiap frame seperti lukisan bergerak. Kamera tidak hanya merekam, tapi memeluk. Sinematografinya mewah tapi tidak sombong, mahal tapi tidak pamer. Yandy dan timnya menciptakan dunia yang terasa sekaligus jauh dan dekat, asing tapi familiar. Ini bukan hanya hasil dari tata artistik yang apik, tapi juga visi yang jelas dan terjaga sejak awal.
Dan keindahan itu tak pernah dibiarkan sendirian. Scoring dalam film ini hadir seperti nyawa kedua. Musik-musik yang mengiringi adegan tak pernah terasa memaksa atau dramatis berlebihan. Justru sebaliknya: ia datang seperti embun, seperti detak jantung yang pelan-pelan mengisi ruang kosong. Musik tidak digunakan untuk menuntun emosi secara paksa, melainkan untuk memperdalam rasa yang sudah tumbuh. Seolah ada dialog senyap antara suara dan gambar, yang saling meneguhkan. Ini adalah scoring yang bukan hanya indah, tapi tahu diri—dan itu, dalam dunia film, adalah kemewahan yang langka.
Sheila Dara memberikan salah satu penampilan terbaik dalam kariernya. Ia tak perlu dialog panjang untuk menunjukkan kelelahan emosional yang terus ia pikul. Raut wajah, gestur tubuh, dan tatapan kosong yang penuh makna—semuanya membuat karakter Sore terasa hidup dan menyentuh. Sementara Dion Wiyoko, dalam perannya sebagai Jonathan, tampil sebagai sosok yang nyata: seorang pria dengan mimpi-mimpi gagal, dengan luka yang tak pernah benar-benar ia obati. Keduanya bukan hanya pasangan dalam cerita, tapi dua manusia yang membawa trauma masing-masing ke dalam hubungan. Dan itu terasa. Terlalu terasa, bahkan.
Yang lebih menarik, film ini tidak memaksa kita untuk mengidolakan siapa pun. Tak ada karakter ideal di sini. Tak ada penyelamat. Yang ada hanya manusia—lelah, bingung, kadang pengecut, tapi tetap mencoba mencintai sebisanya. Dan justru dari sanalah film ini mendapat kekuatannya. Ia tidak menawarkan harapan palsu, tapi juga tidak menyeret kita dalam keputusasaan. Ia hanya berkata: begini lho rasanya hidup.
Namun Sore: Istri dari Masa Depan bukan hanya tentang Sore, atau Jonathan, atau time-loop. Film ini juga secara tidak langsung bicara tentang industri film Indonesia hari ini—yang dalam lima tahun terakhir seperti terjebak dalam jebakan formula menang cepat. Judul-judul horor dirilis beruntun, setan-setannya seperti diundi dari kotak undian, dan cerita-ceritanya seperti ditulis dalam rapat mingguan produksi, bukan dari ruang perenungan kreatif.
Kita, sebagai penonton, seolah dianggap tidak cukup cerdas, tidak cukup sabar, atau tidak cukup ingin merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kejutan jump scare. Tapi Sore: Istri dari Masa Depan hadir sebagai penyangkalan terhadap asumsi malas itu. Ia percaya bahwa penonton Indonesia masih ingin disapa, bukan ditampar; ingin merasakan, bukan sekadar dikagetkan. Dan keberanian untuk percaya pada penonton itulah yang membuat film ini terasa istimewa.
Yandy Laurens, yang sebelumnya dikenal lewat Keluarga Cemara dan proyek-proyeknya bersama Visinema, membuktikan bahwa ia masih konsisten dalam satu hal: memperlakukan cerita dengan hormat, memperlakukan karakter dengan cinta, dan memperlakukan penonton sebagai manusia. Dalam dunia film yang semakin keras mengejar tren, Yandy justru menepi, mengambil waktu, dan dari situ ia menciptakan sesuatu yang tak hanya layak tonton—tapi layak diingat.
Salah satu kutipan dalam film ini berbunyi, “Dunia paralel hanyalah manifestasi kesombongan manusia.” Sebuah kalimat yang mungkin bisa juga dibaca sebagai kritik halus terhadap industri perfilman yang terlalu sibuk mengejar dunia alternatif: pasar yang cepat, untung yang pasti, cerita yang mudah. Padahal dunia nyata—dengan segala kesulitannya, kekerasan emosinya, dan keindahan yang jarang—masih menyimpan begitu banyak cerita yang bisa digali.
Karena pada akhirnya, bioskop bukan hanya tempat untuk melarikan diri. Ia juga bisa menjadi ruang untuk mengingat siapa kita, mencintai siapa yang pernah pergi, dan menerima bahwa tidak semua luka bisa sembuh. Sore: Istri dari Masa Depan melakukan itu semua—dengan kelembutan, dengan keteguhan, dan dengan kejujuran yang kini langka.
Dan kalau film seperti ini masih bisa ada di bioskop kita, maka ada harapan. Bukan hanya untuk industri film, tapi untuk kita semua yang masih percaya pada kekuatan cerita.