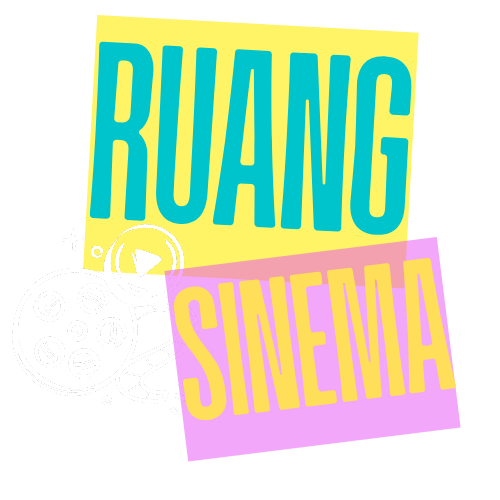Selamat datang di bioskop negeri, tempat segala bentuk kreativitas dikubur hidup-hidup di bawah tumpukan poster film horor murahan dan adaptasi asing yang tak tahu malu. Dulu, orang bilang film adalah cermin kebudayaan. Tapi sekarang, film Indonesia lebih mirip etalase minimarket: semua serba cepat saji, instan, dan tentunya… penuh produk imitasi.
Mari kita bicara jujur, karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Industri film Indonesia saat ini tampaknya lebih layak disebut sebagai “industri pengekor”, atau lebih halusnya: kompilasi karya-karya yang sudah sukses di negara lain lalu dicangkok ke tanah air dengan bumbu lokal seadanya. Dari deretan film horor yang menjamur seperti jamur di musim hujan, kita hanya bisa mengelus dada, dan kemudian merogoh kocek untuk menonton lagi-lagi kisah setan berambut panjang, berkuku tajam, yang suka muncul dari belakang kulkas.
Horor Indonesia kini bukan lagi genre, tapi semacam “jalan ninja” para produser untuk mengejar pundi-pundi. Latah massal ini seakan menjelma menjadi ritual wajib setiap awal tahun: siapa duluan bikin film hantu, dia duluan panen cuan. Cerita? Itu urusan belakangan. Originalitas? Ah, siapa peduli. Penonton toh tetap datang, mau ditakut-takuti dengan efek suara mendadak atau wajah hantu bekas drama YouTube horor.
Lebih menyedihkan lagi, tren adaptasi film luar negeri kini menjadi dalih baru untuk membungkus kemalasan berpikir para sineas dan produser. Lihat saja barisan film Indonesia belakangan ini: satu demi satu mengadaptasi cerita dari Korea, Thailand, bahkan Jepang. Tak ada lagi geliat untuk menciptakan kisah yang lahir dari tanah sendiri. Seolah-olah kisah dari negeri sendiri tidak layak tayang di bioskop sendiri.
Tapi mari kita bertanya: apakah benar penulis skenario Indonesia sudah kehabisan ide? Ataukah mereka hanya tidak diberi ruang untuk bernapas karena produser lebih memilih formula instan? Atau jangan-jangan—dan ini lebih menyedihkan—semua ini hanyalah cara licik untuk mengelabui penonton: menjual cerita asing dengan aktor lokal sebagai upaya menekan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan.
Beginilah logika kebanyakan produser film kita: “Kalau film itu sukses di Korea, ya sudah kita ambil ceritanya. Biar aman. Nggak usah mikir. Yang penting balik modal.”
Dan entah kenapa, selalu ada alasan yang terdengar bijak: “Ini bentuk apresiasi terhadap karya luar.” Padahal kalau kita telusuri lebih dalam, ini bukan apresiasi, tapi reproduksi ide mentah-mentah dengan kemasan lokal. Kalau ini disebut apresiasi, maka mencuri karya tetangga dan mengganti judulnya dengan bahasa Indonesia juga bisa disebut “kolaborasi kultural.”
Sementara itu, legenda-legenda lokal hanya jadi cerita pengantar tidur. Dongeng-dongeng Nusantara, yang kaya makna dan bisa jadi bahan emas sinema, hanya dibiarkan membusuk di rak-rak buku perpustakaan. Apakah kisah Nyai Roro Kidul, Jaka Tarub, atau kisah magis dari Tanah Toraja tidak cukup “menjual”? Atau memang para produser kita tidak cukup mau untuk menggali dan mengembangkan cerita dari akar budaya kita sendiri?
Jika tren ini terus berlangsung, bersiaplah menyambut “mati suri jilid dua” dalam sejarah perfilman Indonesia. Era kejayaan sinema Indonesia hanya akan tinggal mitos yang dikabarkan lewat diskusi Twitter atau pidato sambutan festival film. Sementara penonton yang jenuh akan berpaling: ke streaming luar negeri, ke konten pendek media sosial, atau ke kenangan masa lalu tentang film-film yang pernah membuat mereka bangga sebagai penonton Indonesia.
Dengarkan baik-baik: penonton kita tidak sebodoh yang kalian pikirkan. Mereka bisa membedakan mana film yang dibuat dengan niat dan mana yang hanya jadi mesin uang. Mereka bisa mencium bau amis film daur ulang meski dibungkus dengan sinematografi mentereng dan aktor tampan berotot. Mereka tidak akan terus-menerus beli tiket hanya demi nostalgia palsu atau jumpscare dadakan.
Satu-satunya yang masih percaya bahwa mereka bisa terus mengelabui penonton hanyalah produser yang terlalu sibuk menghitung ROI hingga lupa bahwa mereka sedang membunuh perlahan ekosistem seni yang seharusnya mereka jaga.
Saran saya sederhana: berhentilah menjadi pengekor. Mulailah menjadi pelopor. Jika kalian butuh cerita, Nusantara ini penuh dengan ribuan kisah yang belum tergarap. Jika kalian butuh inspirasi, lihat ke dalam, bukan ke luar. Dan kalau kalian hanya tertarik membuat film demi untung semata, silakan… tapi jangan salahkan kalau suatu hari bioskop kalian kosong, dan yang tersisa hanya gema nostalgia dari masa ketika film Indonesia masih punya harga diri.
– –
Jika tulisan ini terasa pedas, itu artinya tepat sasaran. Karena kritik yang baik bukan untuk menyenangkan, tapi untuk menyadarkan.
Siapa tahu masih ada yang mau mendengar.
Dari saya, pecinta film Indonesia yang rindu karya original para sineas Indonesia.