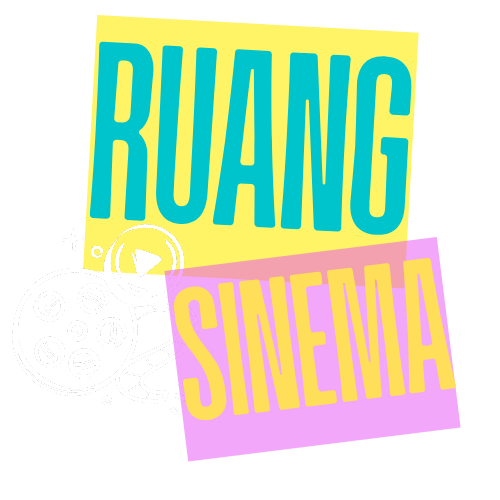Kisah ini dimulai seperti dongeng: sekelompok kreator animasi Indonesia bertekad membuat film nasionalisme yang membanggakan bangsa. Mereka punya semangat, mimpi, dan… dompet yang menipis. Sang sutradara, Endiarto, menamai misi ini “gotong royong”. Di dunia nyata, istilah itu artinya saling membantu. Di proyek ini, artinya: semua orang kerja dengan bayaran exposure dan ucapan “terima kasih”.
Sejak awal, targetnya jelas: bukan untuk mendominasi box office, tapi untuk membuktikan bahwa kemustahilan bisa dilakukan. Dan mereka berhasil — tayang di 16 layar saja di seluruh negeri. “Biar eksklusif,” mungkin begitu kata orang optimis. Padahal realitanya, itu jumlah layar yang bahkan kalah banyak dari jumlah cabang pecel lele di Jabodetabek.
Penonton yang datang dibuat kagum — bukan karena kualitasnya, tapi karena keberanian tim ini merilis animasi yang, menurut netizen, tampak seperti draft kerja kelompok sebelum dosen memberi nilai. Animasi kaku? Check. Karakter seperti figur plastik 3D murah? Check. Audio yang bikin bibir dan suara jalan di timeline berbeda? Double check.
Hanung Bramantyo ikut menimpali. Katanya, bujet Rp6,7 miliar itu “nggak nyampe” untuk film layar lebar. Kalau buat sinetron atau platform streaming, mungkin masih cocok. Artinya: ini bukan inovasi, tapi aksi terjun bebas dari tebing tanpa parasut.
Dan jangan khawatir soal izin tayang — Lembaga Sensor Film sudah memberi lampu hijau. Maklum, LSF cuma periksa soal pornografi dan kekerasan. Kualitas animasi? Nggak masuk pasal. Jadi meskipun mata penonton serasa ditampar efek visual 2008, secara hukum semua aman.
Akhirnya, Merah Putih: One for All jadi legenda baru perfilman Indonesia: bukti bahwa semangat saja tidak cukup. Butuh uang, skill, dan sedikit keberanian untuk mengakui kalau proyek ini seharusnya masih di meja editing, bukan di layar bioskop. Tapi hei, di negara ini, kadang “yang penting jadi” lebih cepat tayang daripada “yang penting bagus”.