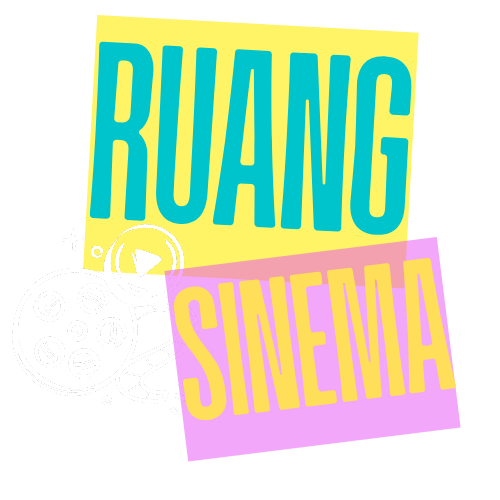Sebuah pembacaan kritis atas drama rumah tangga yang dibalut kemewahan visual, namun menyisakan pertanyaan mendasar tentang keberanian sinema Indonesia menghadirkan realitas emosional yang apa adanya.
Hanung Bramantyo tidak asing dengan genre drama rumah tangga berbalut intrik perselingkuhan. “Ipar Adalah Maut” membuktikan bahwa ia mampu meramu formula melodrama yang mengguncang layar lebar. “La Tahzan” datang seolah sebagai saudara kandung film itu—lebih panjang durasinya, lebih rapi visualnya, namun ironisnya justru kehilangan napas emosional yang membuat kisah serupa terasa hidup.
Kisahnya berpusat pada Alina (Marshanda) dan Reza (Deva Mahenra), pasangan mapan yang hidup di rumah bak katalog arsitektur. Kehidupan mereka mulai goyah saat hadir Asih (Ariel Tatum), pengasuh baru bagi anak mereka. Dari titik ini, film mencoba menelusuri retakan kepercayaan dan godaan yang menyelinap ke ruang keluarga.
Dari segi teknis, “La Tahzan” patut diakui tampil menawan. Komposisi visualnya rapi, tata cahaya menegaskan suasana, dan blocking aktor tertata seperti panggung teater. Bahkan, rumah yang menjadi pusat cerita seolah dirancang sebagai karakter tersendiri-dingin, elegan, dan selalu teratur, kontras dengan gejolak yang seharusnya bergemuruh di dalamnya.
Ariel Tatum memerankan Asih dengan campuran pesona dan manipulasi yang efektif. Ia mengisi layar dengan energi yang membuat penonton tak bisa memalingkan mata. Marshanda, di sisi lain, memberi lapisan emosional yang stabil, meski karakternya sering terjebak menjadi penonton dalam konflik yang menimpa dirinya sendiri. Deva Mahenra berhasil menampilkan ambiguitas tokoh Reza, meski penggarapan karakternya cenderung aman dan terukur.
Namun, kekuatan teknis ini justru menyoroti kelemahan terbesar film: absennya keberanian menggali kedalaman. Alih-alih menyelami motivasi dan dilema batin para tokoh, narasi terjebak dalam lingkaran pertengkaran berulang. Konflik muncul, reda, lalu diulang tanpa eskalasi yang signifikan. Penonton tidak diajak menyelami luka, hanya diajak melihat permukaannya yang mengilap.
Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah “La Tahzan” ingin menjadi drama psikologis yang menelanjangi kompleksitas relasi manusia, atau sekadar melodrama konvensional yang memindahkan estetika sinetron ke layar lebar? Pilihan naratifnya condong pada yang kedua, membuatnya aman secara pasar namun lemah secara tematik.
Ada momen-momen yang seharusnya menjadi titik ledak emosional-tatapan kosong di meja makan, jeda panjang sebelum sebuah pengakuan, atau keheningan di kamar tidur-namun semua itu berakhir seperti properti visual semata, tidak pernah diolah menjadi ledakan dramatis yang membekas. “La Tahzan” tampak lebih tertarik menjaga estetika daripada membiarkan penonton merasakan ketidaksempurnaan yang menyakitkan.
Dalam lanskap sinema Indonesia, ini bukan sekadar soal satu film. Ada pola yang berulang: kisah-kisah rumah tangga yang diolah menjadi tontonan publik lebih sering menekankan sensasi daripada pemahaman. Relasi toksik kerap dijadikan objek voyeurisme yang memikat, tapi jarang dibedah secara jujur. “La Tahzan” tidak melanggar pola itu-ia justru mengukuhkannya.
Padahal, drama rumah tangga adalah salah satu ruang narasi yang paling kaya untuk eksplorasi artistik. Ia membuka kesempatan membicarakan gender, kekuasaan, kelas sosial, bahkan trauma lintas generasi. Namun kesempatan itu hilang ketika cerita memilih berjalan di jalur aman: membungkus masalah dalam rumah yang selalu bersih, emosi yang terukur, dan konflik yang terprediksi.
Keputusan artistik ini mungkin akan memuaskan sebagian penonton yang datang untuk visual cantik dan aktor ternama. Tapi bagi penonton yang mencari keberanian bercerita-kejujuran yang membuka luka, bukan sekadar menunjukkannya-“La Tahzan” akan terasa seperti elegi yang dinyanyikan di balik kaca: indah, tetapi terpisah dari kehidupan yang sesungguhnya.
Sebagai karya, “La Tahzan” tetap memiliki nilai produksi yang patut diapresiasi. Namun sebagai bagian dari percakapan sinema Indonesia yang lebih luas, ia menyisakan pekerjaan rumah: kapan kita akan berhenti takut mengotori estetika demi kebenaran cerita?
Pada akhirnya, film ini mengingatkan bahwa keindahan tidak selalu sinonim dengan kebenaran. Di balik pencahayaan sempurna dan ruang yang tertata rapi, mungkin justru tersembunyi kisah yang paling layak diceritakan—kisah yang menuntut keberanian, bukan sekadar keterampilan teknis. Dan keberanian itulah yang, sayangnya, masih absen dari “La Tahzan”.