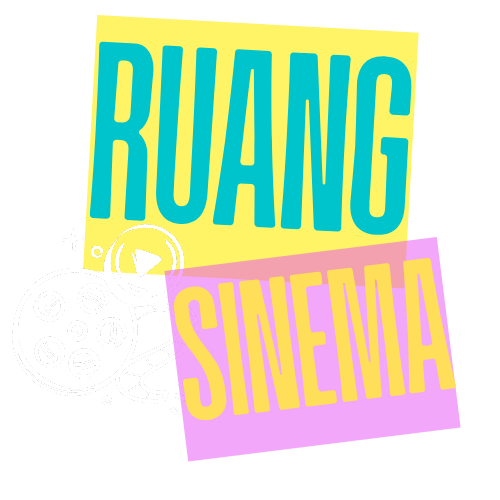Animasi Indonesia sedang berusaha membuktikan dirinya. Setelah sekian lama berkutat pada format aman—film anak, cerita ringan, atau eksperimen yang tidak pernah benar-benar matang—Panji Tengkorak hadir dengan klaim berani: film animasi 2D aksi pertama Indonesia dengan skala penuh. Mengangkat komik klasik karya Hans Jaladara, film ini bukan hanya menawarkan nostalgia, melainkan juga janji besar tentang arah baru animasi lokal. Tetapi justru karena klaim besar itulah, kegagalannya terasa semakin menonjol.
Sebagai karya, Panji Tengkorak penuh dengan paradoks. Ia berani sekaligus ragu, ambisius sekaligus ceroboh. Pada momen-momen tertentu, film ini memukau: duel sengit, darah memercik, tubuh terpotong, dan energi visual yang jarang sekali terlihat dalam lanskap animasi kita. Tetapi di banyak bagian lain, kualitasnya merosot—narasi berputar-putar, ritme tersendat, dan musik yang seharusnya menjadi penguat emosi justru menjadi pengganggu utama.
Narasi yang Tersandung Kilas Balik
Kisah Panji sesungguhnya sederhana. Ia adalah pendekar yang kehilangan istrinya secara tragis, lalu memperoleh kekuatan mistis untuk melanjutkan hidup sekaligus menuntut balas. Namun, alih-alih bergerak lurus, film ini terlalu asyik dengan kilas balik. Hampir setiap fase penting diceritakan ulang, seolah penonton tidak cukup cerdas untuk menangkapnya tanpa penjelasan tambahan. Akibatnya, alur yang mestinya tegas berubah melelahkan. Kilas balik tidak lagi menjadi alat dramatik, melainkan beban yang menggerus momentum.
Lebih parah lagi, di tengah tragedi yang pekat, film ini kerap menyelipkan humor yang dipaksakan. Kehadiran karakter seperti Kuwuk dengan punchline di saat cerita sedang serius membuat tensi emosional runtuh begitu saja. Alih-alih memberi ruang napas, humor semacam ini justru menjadi ironi: film yang mengaku mengusung tragedi malah tak tahan menahan godaan untuk bercanda.
Visual yang Gagah tapi Tidak Konsisten
Tidak bisa dipungkiri, secara visual Panji Tengkorak menyimpan energi besar. Adegan pertarungan dikerjakan dengan koreografi yang cukup solid, menampilkan duel berdarah tanpa kompromi. Untuk pertama kalinya, animasi Indonesia berani keluar dari jalur aman dan menghadirkan kekerasan grafis yang tidak ditujukan untuk anak-anak. Pada titik ini, film patut diapresiasi karena berhasil mendobrak batas psikologis industri yang selama ini terlalu berhati-hati.
Namun keberanian itu terhenti pada konsistensi. Ada adegan yang tampak matang, penuh detail, dan bertenaga, tetapi tak jarang pula kualitas animasi anjlok: gerakan kaku, tekstur murahan, desain karakter kehilangan kedalaman. Seolah ada dua film yang diproduksi bersamaan—satu dengan dedikasi penuh, satu lagi setengah hati. Untuk proyek sebesar ini, inkonsistensi semacam itu lebih dari sekadar kelemahan teknis; ia mencederai klaim bahwa Panji Tengkorak adalah tonggak animasi nasional.
Musik: Luka yang Membuka Diri
Aspek yang paling menghancurkan justru datang dari musik. Tata suara seharusnya menjadi nadi emosional, pengikat yang memperkuat gambar. Tetapi dalam film ini, scoring kerap terdengar salah tempat, bahkan merusak intensitas adegan. Kesalahan paling fatal adalah penggunaan lagu “Bunga Terakhir” di klimaks. Alih-alih menjadi ledakan emosional, lagu itu terasa tempelan, gimmick yang dipaksakan masuk, hingga meruntuhkan suasana yang sedang dibangun.
Kelemahan ini tidak berhenti di klimaks. Sejak awal, musik dipasang terlalu penuh, tanpa jeda, tanpa ruang hening. Padahal justru dalam diam, tragedi bisa bergaung lebih kuat. Film ini seolah tidak percaya pada kekuatan keheningan, padahal sinema selalu memberi ruang bagi yang tak terucap. Akibatnya, alih-alih menguatkan, musik berubah menjadi luka terbuka yang membuat film semakin timpang.
Suara yang Menyelamatkan
Untunglah, ada satu elemen yang menjaga film ini dari kehancuran total: pengisi suara. Denny Sumargo menghadirkan Panji dengan getir dan marah yang meyakinkan. Donny Damara sebagai antagonis Bramantara memberi nuansa licik yang tepat, sementara Aghniny Haque dan Nurra Datau menambah lapisan energi pada karakter pendukung. Performa vokal ini menjadi jangkar, memastikan emosi tetap berdenyut meski visual dan musik kerap terjatuh.
Tonggak yang Rapuh
Panji Tengkorak ingin dikenang sebagai tonggak animasi Indonesia. Dan dalam arti tertentu, ia memang berhasil. Keberanian menghadirkan kekerasan, keberhasilan menjauhkan animasi dari stigma tontonan anak-anak, dan kesungguhan membangkitkan warisan komik lokal adalah capaian yang signifikan. Tetapi tonggak ini rapuh. Ia berdiri, tetapi goyah; tinggi, tetapi retak.
Sebagai film, Panji Tengkorak gagal menemukan keseimbangan. Ambisi melesat tinggi, tetapi eksekusi tertinggal jauh. Narasi repetitif, animasi tak konsisten, musik yang menyesatkan—semuanya membuat film ini lebih mirip draf besar daripada karya matang.
Pada akhirnya, Panji Tengkorak berdiri bukan sebagai mahakarya, melainkan sebagai lonceng tanda jalan baru. Ia mengajarkan bahwa keberanian tidak pernah cukup tanpa kesabaran, dan ambisi selalu menuntut disiplin yang panjang. Dalam ketimpangan inilah, film ini menemukan arti pentingnya—sebagai batu loncatan, bukan batu perhentian.