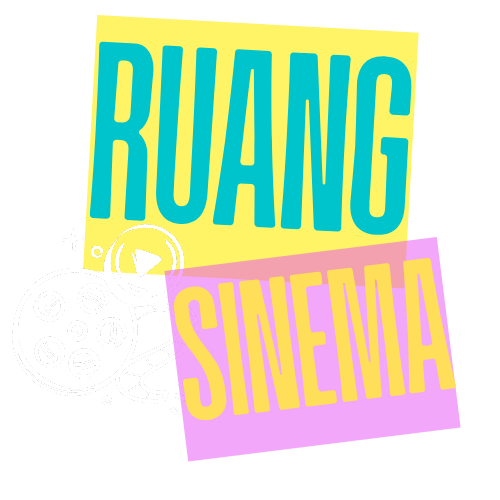Ada sesuatu yang provokatif dalam Tinggal Meninggal. Kristo Immanuel, dalam debut penyutradaraannya, tidak sekadar menghadirkan film komedi gelap, melainkan sebuah pukulan keras terhadap wajah sinema Indonesia yang belakangan ini terlalu nyaman berkutat di lingkaran klise: horor murahan, adaptasi viral instan, drama perselingkuhan adaptasi dari kisah viral atau komedi receh yang sekadar menagih tawa. Di tengah stagnasi itu, Tinggal Meninggal berdiri sebagai pernyataan: film Indonesia masih bisa menghadirkan karya yang berani, segar, dan menyakitkan sekaligus.
Kristo tidak bermain aman. Ia memilih jalan berisiko dengan mengangkat kematian—tema yang biasanya diperlakukan sakral atau melodramatis—menjadi arena satir yang getir. Tinggal Meninggal menguliti bagaimana manusia modern memperlakukan kematian bukan lagi sebagai momen refleksi, melainkan komoditas perhatian. Di tangan Kristo, duka diretas, dijadikan panggung, lalu dipermainkan dalam balutan humor absurd. Hasilnya? Tawa yang pecah, tetapi menyisakan rasa perih di tenggorokan.
Humor di film ini bekerja seperti pisau bermata dua. Hampir semua punchline mendarat tepat, bukan karena ia sekadar lucu, melainkan karena konteksnya begitu dekat dengan absurditas sosial kita. Dari obrolan random hingga ledakan satir, semuanya diramu dengan presisi. Kristo tidak menjual lelucon murahan; ia menempatkan humor sebagai instrumen kritik sosial yang efektif. Maka ketika penonton tertawa, sebenarnya kita sedang mentertawakan diri sendiri—kehausan kita akan validasi, kecenderungan menyepelekan duka, hingga kegagapan kita menghadapi kesepian.
Namun di balik lapisan satir itu, Tinggal Meninggal adalah potret getir tentang keterasingan. Gema, sang tokoh utama, hadir sebagai cermin bagi penonton. Ia haus perhatian, rapuh, dan terjebak dalam lingkaran isolasi emosional. Bahkan ketika film memecah dinding keempat, Gema berbicara langsung kepada kita—dan kita refleks menjawabnya, karena keresahannya terlalu akrab. Di sini, Kristo cerdik: ia tidak sekadar membangun karakter, tapi menghadirkan wadah proyeksi, tempat penonton berhadapan dengan versi terburuk dari diri mereka sendiri.
Sinematografi film ini memperkuat lapisan psikologis tersebut. Pilihan framing yang sempit, pencahayaan kamar redup, hingga komposisi visual yang menekankan keterasingan—semuanya mempertegas tema kehilangan. Bahkan ketika kamera bermain lebih longgar di momen komedi, ada sensasi pahit yang tetap menggantung. Dan di atas semua itu, skor musiknya bekerja sebagai hantaman terakhir: epik, mencekam, dan tak jarang membuat bulu kuduk meremang. Musik di sini bukan sekadar ilustrasi, melainkan suara batin yang menolak diam.
Durasi dua jamnya padat, tanpa ruang untuk kelesuan. Setiap adegan terikat rapi dalam struktur naratif yang mengalir mulus. Kristo tidak memberi kesempatan penonton bernapas terlalu lama; ia tahu kapan harus menekan dengan dialog lirih, kapan meledakkan tawa satir, dan kapan menggiring kita ke dalam renungan pahit. Film ini bergerak seperti spiral, mulai dari humor ringan, menuju absurditas, lalu jatuh ke jurang eksistensial yang gelap. Dan spiral itu terasa begitu alami, bukan sekadar permainan naskah yang dipaksakan.
Kekuatan terbesar Tinggal Meninggal justru ada pada keberaniannya melawan arus. Di saat industri film Indonesia masih sibuk dengan horor formulaik dan komedi televisi yang diangkat ke layar lebar, film ini tampil sebagai tamparan keras. Ia menunjukkan bahwa sinema lokal masih bisa mengejutkan, masih bisa menohok, dan masih bisa membuat kita keluar bioskop dengan dada sesak sekaligus lega. Kristo berhasil membuktikan diri sebagai suara baru yang patut diperhitungkan, seorang sutradara yang tidak takut membuat penonton tidak nyaman.
Namun, film ini bukan tanpa cacat. Ada beberapa bagian yang terlampau indulgent, terutama pada beberapa transisi humor yang bisa terasa repetitif. Akan tetapi, kekurangan ini kecil dibanding keberanian dan orisinalitas yang ditawarkan. Jika film-film Indonesia lain kerap bermain aman, Tinggal Meninggal justru memilih jalur berbahaya, dan menang.
Apa yang membuat film ini layak dicatat dalam sejarah perfilman kita adalah kejujurannya. Tidak ada lapisan manis untuk menutupi getirnya kehilangan. Tidak ada kompromi untuk menyenangkan semua kalangan. Film ini tahu dirinya pahit, dan justru karena itu terasa otentik. Ia mengajarkan bahwa sinema tidak selalu harus menjadi hiburan escapist; kadang ia harus menjadi cermin yang retak, yang memaksa kita menatap luka yang kita hindari.
Di tengah banjir film horor viral, drama perselingkuhan yang menjemukan, atau komedi murahan yang beredar di bioskop, Tinggal Meninggal hadir sebagai oasis yang menyegarkan—meski dengan rasa getir. Film ini bukan sekadar hiburan, melainkan pernyataan artistik: bahwa sinema Indonesia masih bisa menggigit, masih bisa relevan, dan masih bisa membuat kita bangga.
Pada akhirnya, Tinggal Meninggal adalah karya yang pantas disebut sebagai tonggak baru. Sebuah komedi gelap yang bukan hanya berhasil membuat kita tertawa, tetapi juga menangis, merenung, bahkan marah. Film ini adalah sindiran, elegi, sekaligus selebrasi keberanian. Dan jika ada satu hal yang ingin saya tekankan, itu adalah: sinema Indonesia butuh lebih banyak film seperti ini—film yang tidak takut membuat kita tinggal merenung, setelah meninggalkan bangku bioskop.