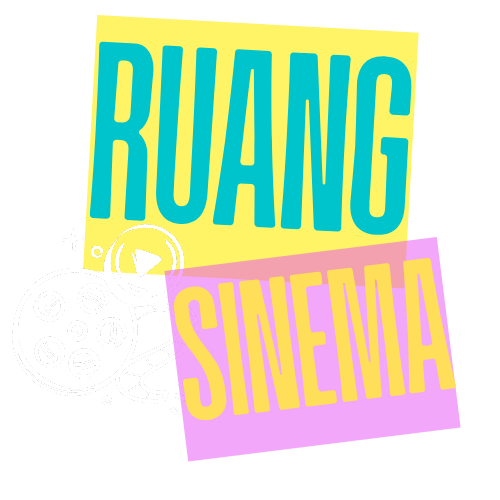Ada kecenderungan dalam sinema Indonesia kontemporer, terutama pada genre religi perempuan, di mana penderitaan tokoh utamanya dijadikan medium utama untuk mencapai ‘kebangkitan spiritual’. Film “Assalamualaikum Baitullah” (2025), disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu dan diadaptasi dari novel Asma Nadia, adalah salah satu manifestasi terbaru dan paling eksplisit dari pola ini.
Alih-alih menjadi refleksi atas perjalanan iman perempuan modern, film ini justru memperlihatkan bagaimana luka, pengkhianatan, dan trauma emosional dijadikan ladang dakwah. Bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk menundukkan. Bukan untuk memberdayakan, melainkan untuk memurnikan.
Perempuan, Penderitaan, dan Tuhan: Trias Patriarkal yang Dibungkus Spiritualisme
Amira (diperankan Michelle Ziudith) adalah perempuan tak beranak yang ditinggal suaminya, Pram (Miqdad Addausy), lalu mencoba bunuh diri setelah tahu diselingkuhi. Ia kemudian ‘diselamatkan’ oleh Barra (Arbani Yasiz), sahabat masa kecil yang kini menjadi jembatan antara luka dan ketenangan spiritual. Formula ini, meskipun terdengar familiar, sebenarnya adalah naskah berulang dari banyak film sejenis: perempuan harus jatuh sedalam-dalamnya agar pantas mendapatkan kasih Tuhan.

Film ini tidak membangun emosi secara organik. Masalah dilemparkan langsung di menit-menit pembuka: Pram telat pulang, Amira curiga, Pram pergi selingkuh, Amira hancur. Tidak ada ruang untuk mengenal siapa Amira sebelum trauma, atau mengapa relasi mereka gagal. Semua hanya disajikan sebagai data pendukung agar adegan-adegan ratapan terasa sahih. Inilah bentuk dakwah yang dilandaskan pada kekosongan psikologis, bukan pada kedalaman pengalaman manusia.
Michelle Ziudith tampil total, tentu saja. Wajahnya yang sendu, tatapan kosongnya, tubuhnya yang nyaris tanpa gestur agresif—semuanya paket lengkap dari karakter perempuan yang dikorbankan oleh naskah. Tapi justru karena film ini terlalu memonopoli narasi untuk penderitaan Amira, karakter lain seperti Amel (Tissa Biani) atau bahkan Pram sendiri, hanya menjadi fungsi dalam orbit tokoh utama. Mereka bukan manusia utuh, melainkan alat naratif.
Dan inilah penyakit utama “Assalamualaikum Baitullah“: ia bukan kisah manusia, tapi ilustrasi dogma.
Dakwah atau Dramatisasi?
Yang paling menonjol dari film ini bukanlah alur atau dinamika konflik, melainkan kecanggihan produksi visual dan desain musik. Sinematografi megah, terutama saat menampilkan Baitullah dalam warna-warna hangat dan tata gambar yang simetris, menciptakan kesan spiritual—tapi hanya di permukaan. Kamera memperlakukan tempat suci bukan sebagai ruang batin yang penuh makna, tapi sekadar latar pengukuhan iman karakter utama.
Skor musiknya juga tidak membantu. Melodrama diperkuat lewat tata suara dan latar musik sentimental yang diputar berulang-ulang, mendorong penonton untuk larut dalam kesedihan tanpa pernah diajak bertanya kenapa. Emosi bukan dibangun dari perjalanan batin tokoh, melainkan dari repetisi tangisan dan monolog spiritual yang dirancang untuk menguras air mata.
Hadrah Daeng Ratu, dengan reputasinya sebagai sineas film religi perempuan, tampaknya terlalu nyaman bermain di jalur yang sama. Dibanding “Pantaskah Aku Berhijab” (2024) yang setidaknya mencoba mengangkat pertanyaan-pertanyaan identitas dan pilihan hidup perempuan dalam konteks agama, “Assalamualaikum Baitullah” lebih memilih jalur aman: perempuan yang tersakiti, lalu ‘diselamatkan’ lewat kepasrahan.
Kritik Terhadap Pola Naratif yang Mengurung Perempuan
Pertanyaan penting yang diajukan film ini—atau justru gagal diajukan—adalah: mengapa perempuan dalam film-film religi harus selalu jatuh, terinjak, bahkan nyaris mati, sebelum dianggap pantas kembali ke Tuhan?
Narasi seperti ini bukan hanya lelah secara estetika, tetapi juga bermasalah secara etis. Ia memaksa penonton untuk mengafirmasi ide bahwa penderitaan adalah harga yang wajar untuk keselamatan rohani. Lebih buruk lagi, ia memperlihatkan bahwa solusi dari pengkhianatan, kehampaan rumah tangga, dan percobaan bunuh diri, adalah ‘menyerah’ secara spiritual, bukan bangkit secara manusiawi.
Narasi ini juga memperlihatkan bagaimana ruang agensi perempuan dikebiri secara halus melalui semangat religiusitas. Tidak ada perlawanan, tidak ada perdebatan batin yang kompleks. Bahkan proses istikharah, yang seharusnya menjadi ruang kontemplasi pribadi yang dalam, diperlakukan layaknya formalitas dramatik—cukup berserah, cukup menangis, lalu semuanya selesai. Ketika perempuan marah, mereka didiamkan oleh alur. Ketika mereka berontak, kamera segera menggiring mereka kembali ke sajadah.
Di sini, film ini tidak lagi bicara soal iman, melainkan pengendalian narasi. Perempuan tidak diberi ruang untuk menawar atau bertanya. Amira tidak pernah benar-benar sembuh—ia hanya belajar menerima. Dan itu disebut cukup.
Penutup: Religius, tapi Tidak Reflektif
Sebagai film religi, “Assalamualaikum Baitullah” berhasil menyentuh emosi pemirsanya lewat kemasan yang lembut dan penampilan pemain utama yang memikat. Namun sebagai karya sinema, film ini terlalu tunduk pada naskah dogmatis yang tidak memberi ruang untuk dialektika, pertumbuhan karakter, atau bahkan harapan yang rasional.
Ini adalah sinema yang menenangkan bagi mereka yang tidak ingin bertanya. Tapi bagi penonton yang mencari film sebagai ruang kontemplasi, bukan sekadar afirmasi, “Assalamualaikum Baitullah” adalah pintu yang tertutup rapat.
Jika kritik ini berdiri di depan pintu Baitullah, maka izinkan ia mengetuk bukan untuk menghakimi, tapi untuk bertanya—dengan suara jujur dan terbuka—apakah semua penderitaan ini memang bagian dari jalan spiritual, atau hanya konstruksi naratif yang terus diproduksi ulang agar perempuan tetap patuh, tetap diam, dan tetap menderita dengan senyuman.