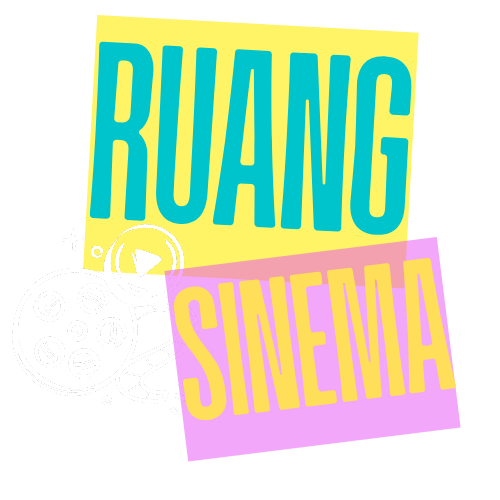Apa jadinya jika kegelisahan sosial kelas menengah-atas soal penampilan dan pencitraan dikemas dalam bungkus body horror, tapi dieksekusi setengah matang? Jawabannya ada di “A Normal Woman“, film terbaru dari Lucky Kuswandi dan ditulis bersama Andri Cung yang tayang di Netflix mulai tanggal 24 Juli 2025. Film ini sebenarnya punya niat baik namun tersesat di antara simbolisme dangkal, pacing mematikan, dan horor estetika ala sinetron prime time.
Film ini mencoba menyamar sebagai thriller psikologis, tapi lebih sering terasa seperti iklan suplemen kesehatan yang berubah jadi mimpi buruk. Dan bukan mimpi buruk yang mengguncang, tapi seperti gatal alergi yang tak kunjung sembuh—mengganggu, menjengkelkan, tapi tidak mematikan.
Dunia yang Terlalu Bersih
Marissa Anita memerankan Milla, seorang ibu dan istri dari keluarga pebisnis suplemen “Eternity Life.” Di luar, dia sempurna: cantik, langsing, elegan, hidup mapan di rumah modern minimalis. Tapi tubuhnya mulai rusak—secara harfiah. Ia digerogoti ruam, luka, dan muntah darah bercampur pecahan kaca. Horor tubuh ini adalah metafora tentang tekanan menjadi “wanita ideal” versi masyarakat kelas menengah urban: selalu terlihat flawless, selalu tersenyum, bahkan saat tubuh mulai menjerit.
Sayangnya, semua itu disampaikan dengan cara yang klise. Kita sudah pernah melihat ini sebelumnya: wanita mapan yang dihancurkan oleh standar sosial, lalu tubuhnya menjadi alat resistensi. Film seperti “Black Swan” atau “Swallow” sudah melakukan itu dengan lebih subtil dan mengguncang. “A Normal Woman” seakan mengulang pola lama tanpa menambahkan sudut pandang baru.
Masalah Tempo dan Gaya
Masalah terbesar film ini ada di tempo dan gaya visual. Dengan durasi hampir dua jam, narasi berjalan pelan, terlalu pelan. Seperti menonton seseorang yang menyisir rambut selama dua jam, tapi sisirnya patah dari menit ke-20. Kita hanya menunggu—dan menunggu—sampai sesuatu yang “besar” terjadi. Tapi tak pernah benar-benar meledak.
Gaya visualnya pun tidak membantu. Sinematografi terlalu bersih, terlalu “cinematic” dalam pengertian iklan properti. Warna pastel, pencahayaan soft, bahkan efek-efek tubuh rusak Milla terlihat seperti tempelan digital tanpa rasa. Ada satu momen ketika darah mengalir dari hidungnya, tapi yang terasa hanya efek CGI murahan yang tidak membangkitkan emosi apapun.
Simbolisme dan Drama Melelahkan
Film ini terlalu cinta pada simbolisme fisik. Gatal di kulit = tekanan batin. Muntah darah = meledaknya emosi terpendam. Rambut rontok = kehilangan kendali. Semua disampaikan secara literal, tanpa ada lapisan pemaknaan yang menggigit. Ini membuat penonton cepat merasa bosan karena film terus-menerus “menjelaskan” alih-alih mengajak kita menyelami.
Lebih parah lagi, subplot hubungan ibu-anak antara Milla dan Angel (diperankan Mima Shafa) justru menjadi soap opera yang melelahkan. Angel merasa ibunya tidak cukup suportif; Milla merasa putrinya terlalu lemah. Tapi konflik itu tidak pernah sampai ke tahap konfrontasi bermakna. Semuanya terasa datar, seperti kutipan motivasi dari Instagram yang dipaksakan jadi skrip film.
Akting: Satu-Satunya Penyelamat
Meski naskahnya kedodoran, performa Marissa Anita patut diapresiasi. Ia mampu menampilkan sosok Milla dengan keanggunan yang perlahan-lahan hancur. Ada saat-saat di mana tatapan kosongnya jauh lebih tajam dari dialog-dialog yang ditulis untuknya. Namun, dia sendirian. Karakter-karakter lain tak diberi cukup ruang untuk berkembang. Bahkan ketika muncul karakter Erika (diperankan Gisella Anastasia), yang seharusnya bisa menambah lapisan baru pada cerita, ia hanya menjadi alat plot tanpa bobot emosional.
Di Antara Kritik Sosial dan Eksploitasi Estetika
Film ini ingin menjadi kritik sosial tentang bagaimana masyarakat menekan perempuan untuk selalu tampil “normal.” Tapi pendekatannya terlalu aman dan estetis. Ketimbang menyelam dalam isu kompleks seperti body dysmorphia, citra media, dan kelas sosial, film justru sibuk menampilkan visual ruam-ruam kulit dan muntahan darah sebagai simbol kosong.
Alih-alih menjadi komentar tajam terhadap budaya toxic femininity dan citra palsu, “A Normal Woman” terjebak dalam estetika eksotis yang malah mengeksploitasi penderitaan karakter utamanya. Ini bukan perlawanan, ini parade penderitaan yang disajikan dengan filter Instagram.
Penutup: Bukan Buruk, Tapi Tidak Berani
“A Normal Woman” bukan film buruk. Tapi ia adalah film yang takut mengambil risiko. Ia punya semua elemen untuk jadi sesuatu yang revolusioner—isu yang relevan, aktris yang mumpuni, bahkan ruang sinematik yang jarang digarap di Indonesia. Tapi semua itu diredam oleh eksekusi yang terlalu hati-hati dan simbolisme yang terlalu literal.
Film ini semestinya bisa jadi batu loncatan penting bagi genre thriller psikologis lokal yang lebih berani menggali sisi gelap perempuan modern. Namun alih-alih menusuk, ia justru memilih untuk menyentuh permukaan secara sopan, seolah takut membuat penonton tak nyaman. Padahal, ketidaknyamanan justru adalah inti dari horor yang efektif.
Sayangnya, “A Normal Woman” memilih jalan aman. Ia seperti peserta lomba kecantikan yang pandai menjawab pertanyaan juri, tapi tak pernah benar-benar punya sikap. Semua terlihat rapi, tapi tidak punya jiwa. Semua disusun indah, tapi hampa.
Bagi sebuah film yang berjudul “A Normal Woman“, ironisnya, ia justru terlalu “normal.” Tidak mengguncang, tidak memberontak, tidak membekas. Ia hadir, meluncur di permukaan, dan menghilang begitu saja—seperti iklan suplemen kesehatan yang dijanjikan menyehatkan, tapi rasanya hambar dan cepat dilupakan.