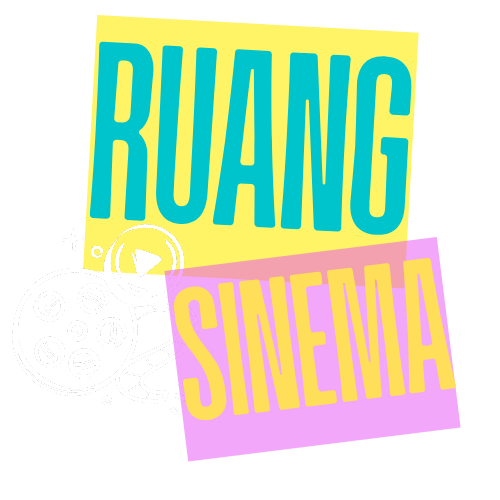Dalam lanskap sinema horor Indonesia yang makin dipenuhi oleh repetisi tanpa refleksi, “Kitab Sijjin & Illiyyin” datang sebagai kejutan. Bukan hanya kelanjutan dari semesta Sijjin, film ini justru hadir sebagai kritik terhadap formula horor lokal yang terlalu lama bertumpu pada jumpscare, suara gamelan, dan perempuan kerasukan tanpa karakterisasi. Alih-alih sekadar menakut-nakuti, film ini memilih jalur yang lebih gelap, lebih dingin, dan—yang paling penting—lebih dalam secara naratif.
Sutradara Hadrah Daeng Ratu, yang sebelumnya dikenal dengan gaya horor konvensionalnya, akhirnya keluar dari zona aman dan menciptakan karya yang benar-benar menyiksa penonton—secara psikologis maupun moral. Di tangan Hadrah, horor bukan cuma genre, melainkan perangkat untuk membongkar luka sosial, kekerasan struktural, dan mitos religius yang selama ini diterima begitu saja.

Film ini mengangkat tokoh Yuli, perempuan yang hidupnya direnggut sejak kecil: orang tuanya tewas, ia dicap anak haram, dan tumbuh dalam keluarga yang memperlakukannya seperti budak. Tapi film ini tak menjual penderitaan Yuli sebagai sensasi. Trauma yang dialaminya disusun bukan untuk mencuri simpati, melainkan untuk membangun karakterisasi yang kompleks—dari sosok yang lembut menjadi perempuan yang dingin dan penuh dendam. Keputusannya untuk mendatangi dukun dan menempuh jalan santet bukan muncul tiba-tiba, tapi dibentuk lewat tumpukan luka yang lama terkubur.
Yunita Siregar menampilkan performa terbaiknya sejauh ini. Ia tidak berakting untuk memancing empati, tapi menjelma sebagai sosok penuh ambivalensi: korban sekaligus pelaku, manusia yang terperosok bukan karena kelemahan, tapi karena dunia di sekitarnya terlalu kejam untuk dimaafkan. Gesturnya kaku tapi penuh makna, ekspresi wajahnya datar tapi menyimpan bara. Transformasinya dari gadis baik menjadi monster spiritual tidak meledak-ledak, tapi justru mengerikan karena dilakukan dalam diam.
Tidak kalah mencolok adalah penampilan Dinda Kanya Dewi sebagai ibu rumah tangga tiran. Ia memerankan sosok yang sering kita jumpai dalam banyak rumah tangga Indonesia: manipulatif, otoriter, tapi berlindung di balik moralitas. Karakternya membingkai realitas sosial yang seringkali tidak tersentuh film horor—bahwa kekerasan tak melulu datang dari sosok laki-laki bertato, tapi bisa lahir dari rahim keluarga sendiri. Kawai Labiba juga mencuri perhatian sebagai karakter yang kerasukan. Ia berhasil memberi intensitas yang mengerikan tanpa harus menjerit atau berlebihan, dan menjadi titik klimaks emosional di paruh akhir film.
Dari sisi teknis, film ini tampil solid. Tata suara yang menusuk dan atmosfer yang membekap tidak sekadar menjadi pelengkap, melainkan elemen dramaturgi itu sendiri. CGI yang digunakan tidak berlebihan, efek praktikal seperti mata keluar, darah menetes dari bibir mayat, dan simbol-simbol mistik di kulit mayat benar-benar dibuat dengan detail. Sinematografi pun mendukung narasi: sudut-sudut sempit rumah Ambar menciptakan klaustrofobia emosional, seolah semua karakter sedang dikurung oleh dosa mereka masing-masing.
Namun pencapaian paling mengesankan justru terletak pada cara film ini mengintegrasikan unsur religius tanpa menjadi khotbah. Judul “Sijjin” dan “Illiyyin” bukan sekadar hiasan Arabisasi, melainkan simbol moral yang menjadi inti konflik. Sijjin adalah catatan amal orang berdosa, sedangkan Illiyyin adalah catatan amal orang beriman. Ketika Yuli harus menuliskan nama-nama korbannya ke dalam jasad manusia, pertanyaan besar pun mengemuka: siapa yang pantas dicatat dalam Sijjin? Apakah orang-orang yang menyakitinya, atau Yuli sendiri yang memilih balas dendam?
Film ini memang tidak luput dari kelemahan. Beberapa eksposisi terasa terlalu gamblang, seolah tidak percaya pada kecerdasan penonton. Alur konflik utama juga bisa ditebak dari trailer, dan beberapa adegan terasa terlalu cepat dalam penyelesaiannya. Tapi kekurangan-kekurangan itu terasa kecil ketika dibandingkan dengan keberanian film ini dalam mengeksplorasi tema.
Yang dilakukan Hadrah dalam “Kitab Sijjin & Illiyyin” adalah kerja restorasi genre. Ia tidak menawarkan horor sebagai hiburan instan, tapi sebagai pengalaman eksistensial. Film ini mengajak penonton tidak hanya takut pada setan, tapi juga pada diri sendiri. Bahwa dalam setiap luka, tersembunyi benih kebencian yang bisa tumbuh menjadi kutukan paling nyata.
Penutup:
“Kitab Sijjin & Illiyyin” bukan sekadar film horor. Ini adalah pernyataan. Bahwa perempuan bisa memegang kendali atas horor, tidak hanya sebagai korban, tapi juga sebagai perancang teror. Bahwa sinema bisa menakutkan bukan karena makhluk gaib, tapi karena ia berani menyorot kemunafikan manusia. Dan bahwa film horor Indonesia, jika digarap dengan tekun, bisa mencapai kedalaman artistik yang tak kalah dari film drama sekalipun.
Jika ada satu film horor Indonesia yang patut dikenang tahun ini—bukan karena seberapa keras penontonnya menjerit, tapi karena seberapa tajam ia menggores kesadaran—”Kitab Sijjin & Illiyyin” adalah jawabannya.