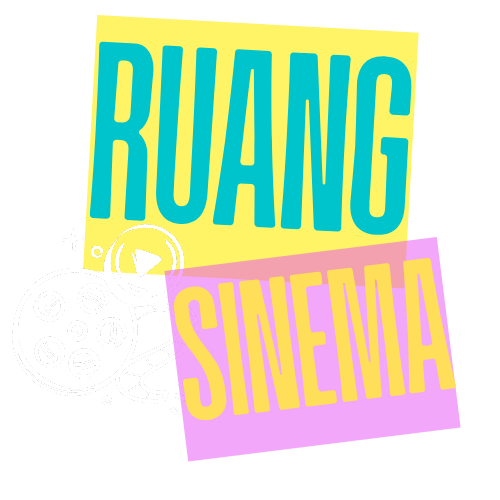Film Omniscient Reader: The Prophecy seharusnya menjadi perayaan bagi karya sastra digital Korea yang telah mengumpulkan jutaan pembaca di seluruh dunia. Namun yang terjadi justru sebaliknya: ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah adaptasi bisa menjadi penghancuran total terhadap narasi, karakter, dan esensi yang membentuk sumber aslinya. Film ini bukan hanya gagal sebagai karya sinematik, tetapi juga menunjukkan ketidakhormatan yang dalam terhadap cerita yang menjadi fondasinya.
Dalam durasi hampir dua jam, film ini dengan gamblang memperlihatkan bagaimana strategi adaptasi yang tidak dipahami dan dijalankan secara asal-asalan justru melucuti nilai-nilai inti dari kisah yang begitu berlapis. Setiap elemen krusial yang membuat Omniscient Reader’s Viewpoint begitu dicintai—kompleksitas psikologis, kekuatan karakter perempuan, relasi antartokoh, kritik sosial yang tajam—dipangkas habis demi membentuk narasi standar yang nyaman bagi pasar laki-laki muda yang enggan berpikir panjang.
Diangkat dari webnovel Omniscient Reader’s Viewpoint karya Sing Shong, cerita aslinya adalah tentang trauma, pengorbanan, serta keteguhan manusia dalam menghadapi kehancuran. Cerita ini menyuguhkan spektrum karakter yang kompleks: dari Kim Dokja yang rapuh namun konsisten, Yoo Joong-hyuk yang terobsesi namun bermakna, hingga Jung Hee-won dan Yoo Sangah yang menyajikan keberanian perempuan dalam lanskap penuh kekacauan. Namun di tangan sineas yang tampaknya hanya membaca sinopsis dan tergiur ketenaran aktornya, semua ini hilang tak bersisa.
Karakterisasi yang dihapus dan digantikan fantasi laki-laki
Jung Heewon, salah satu tokoh sentral dalam novel, dikenal sebagai sosok perempuan yang memilih jalan keadilan setelah mengalami trauma. Ia digambarkan sebagai pribadi yang rapuh namun tegas, penuh amarah namun juga menyimpan rasa kemanusiaan yang tinggi. Di film, seluruh dimensi ini dihilangkan. Ia hanya ditampilkan sebagai karakter pelengkap, berpenampilan marah tanpa alasan jelas, minim dialog, dan tidak memiliki latar belakang yang memberi makna pada tindakannya. Karakter yang dibangun dengan luka dan pilihan justru dilucuti menjadi wajah kosong dengan pistol di tangan.

Hal serupa terjadi pada Yoo Sangah. Dalam versi asli, ia adalah sosok tenang yang mampu berpikir jernih di tengah kekacauan, mewakili kekuatan yang tidak berteriak. Namun dalam film, ia hanya menjadi stereotip lama: perempuan penyembuh, lembut, jinak, dan sepenuhnya terdefinisi oleh kehadiran tokoh laki-laki. Tidak ada jejak dari keberanian atau nalar kritis yang melekat pada versi awalnya. Penghapusan karakter perempuan kuat seperti ini bukan sekadar masalah naratif, tapi juga mencerminkan bagaimana adaptasi ini dijalankan tanpa sensitivitas atau pemahaman.
Kim Dokja yang kehilangan seluruh identitasnya
Kim Dokja dalam novel bukanlah protagonis konvensional. Ia kompleks, penuh keraguan, dan bertransformasi melalui penderitaan dan pilihan-pilihan sulit. Semua itu hilang dalam film. Tokoh utama ini ditampilkan dengan satu ekspresi sepanjang cerita, kosong dari konflik batin, tanpa ketegangan emosional, dan sepenuhnya kehilangan suara internal yang menjadi ciri khas narasinya. Transformasi emosional yang seharusnya menjadi pendorong utama alur, berubah menjadi deretan adegan tak bermakna.
Sementara itu, Yoo Joong-hyuk, yang dalam novel merupakan karakter penting dan simbol kegagalan yang terus mencoba lagi, dikerdilkan menjadi figur pelengkap. Hubungan antar keduanya, yang menjadi jantung emosional dan filosofis cerita, dipotong dan direduksi menjadi interaksi hambar tanpa dinamika berarti.
Penghinaan terhadap materi sumber
Kesalahan terbesar film ini bukan pada keputusan teknis, melainkan pada arogansi kreatif. Alih-alih menerjemahkan dan memelihara kekuatan utama narasi aslinya, film ini memilih untuk mengubah hampir segalanya. Bahkan elemen-elemen simbolik seperti hubungan karakter, sistem dunia, hingga tema sentral tentang pencarian makna dalam penderitaan, ditanggalkan dan diganti dengan plot datar yang tak memiliki kedalaman atau arah.
Tidak ada niat untuk memahami cerita, hanya keinginan untuk menjual nama besar dan memuaskan segmentasi pasar tertentu. Ini bukan adaptasi, tapi eksploitasi. Bukan interpretasi, tapi komersialisasi kasar yang menjadikan cerita orisinal sebagai korban.
Penutup: Sebuah kegagalan di balik nama besar
Omniscient Reader: The Prophecy adalah kegagalan yang nyaris sempurna. Gagal secara estetika, gagal secara naratif, dan terutama gagal secara etis. Ini bukan sekadar film yang buruk. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap pembaca, penulis, dan siapa pun yang menghargai kekuatan cerita yang disampaikan dengan jujur.
Jika film ini dimaksudkan untuk memperkenalkan cerita Omniscient Reader’s Viewpoint kepada khalayak yang lebih luas, maka misi itu gagal sejak detik pertama. Yang tersisa hanyalah kerusakan reputasi, kemarahan penggemar, dan satu pelajaran pahit: tidak semua cerita layak dijadikan film, terlebih jika tidak dipahami sejak awal.
Film ini layak dilupakan. Cerita aslinya pantas dikenang.