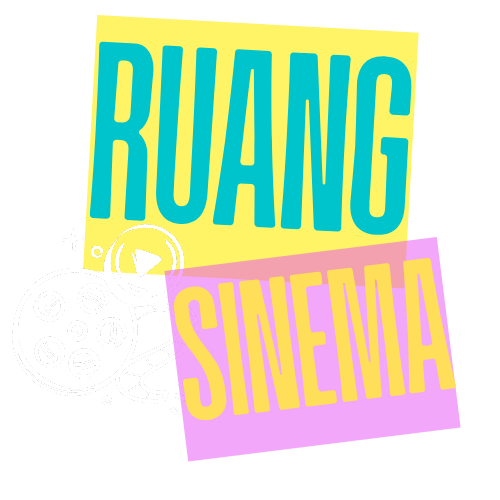Satu kakak, tujuh ponakan, dan satu set premise yang terasa menjanjikan namun akhirnya hanya menjual wacana. “1 Kakak 7 Ponakan” karya Yandy Laurens mengajak penonton untuk menyusuri kisah keluarga yang konon menyentuh dan sarat nilai, tapi sayangnya terlalu sering hanya menyentuh permukaan, nyaris tanpa keberanian untuk benar-benar menggali kedalaman luka, kemiskinan struktural, atau trauma keluarga secara sinematik.
Film ini memulai langkahnya dengan satu janji manis: menggambarkan potret generasi sandwich—anak muda yang harus menunda impian pribadi demi mengurus beban keluarga. Namun, janji itu hanya sebatas jargon. Konflik tidak dikuliti, melainkan dibiarkan menjadi tempelan sentimental, dikemas dengan scoring yang terlalu sadar diri ingin mengundang tangis. Ini bukan penghayatan, ini pengondisian. Musik menjadi kruk yang menopang narasi yang sering kehabisan tenaga. Bahkan Sal Priadi, yang suara seraknya sudah cukup membuat hati goyah, kali ini hanya jadi perias emosi palsu.
Sebagai tokoh utama, Moko mestinya menjadi pusat gravitasi naratif. Tapi sayangnya, gravitasi itu tak cukup kuat untuk menarik penonton masuk ke dalam dilema batinnya. Ia menangis, ia marah, ia frustrasi—tapi semua itu terasa seperti daftar tugas yang harus diselesaikan dalam sebuah film drama keluarga. Emosi tidak mengalir, hanya dikirim via ekspresi yang dibingkai rapi dalam sinematografi bernuansa keemasan. Ini sinema yang lebih tertarik pada penampakan ketimbang pendalaman. Golden hour lighting tidak serta-merta menciptakan kehangatan jika naskahnya terasa dingin.
Lebih jauh, naskah film ini seperti bangunan yang dibangun dari potongan-potongan konsep yang tidak tersambung dengan solid. Kemunculan karakter Ais, misalnya, terasa seperti plot device yang dilempar ke layar tanpa pertimbangan dramaturgis. Ia hadir seperti hantu naratif—muncul tiba-tiba, membawa twist, lalu menghilang tanpa bobot. Logika cerita pun jadi korban. Kita disuruh percaya pada pertemuan kebetulan yang terlalu malas untuk dijelaskan. Ini bukan magis, ini ceroboh.
Ada momen-momen yang seharusnya “meledak”, tapi malah hanya bergema kosong. Adegan kemarahan Moko yang katanya berada “di puncak emosi” justru jatuh menjadi teaterikal tanpa inti. Banyak karakter hanya menjadi dekorasi emosional, numpang lewat tanpa fungsi. Padahal, jika film ini memang ingin menggali makna keluarga, maka setiap relasi seharusnya punya peran dramaturgis, bukan sekadar ornamen.
Yandy Laurens jelas punya reputasi dan sentuhan khas yang bisa dikenali—kelembutan, perhatian pada detail kecil, dan upaya menjadikan keluarga sebagai semesta mikro yang reflektif. Tapi di sini, ia seperti kehilangan kompas. Film ini seperti ingin jadi puisi, tapi patah irama. Ingin jadi lagu, tapi salah nada. Ingin jadi dokumenter emosional, tapi malah jadi brosur motivasi.
Salah satu penyelamat dalam film ini mungkin adalah performa Kawai Labiba, yang di tengah naskah lemah dan pengarahan karakter yang ragu-ragu, masih mampu menciptakan momen autentik. Adegan tangisnya adalah satu-satunya titik di mana emosi terasa mentah dan benar-benar datang dari tubuh karakter, bukan dari keinginan pembuat film untuk memanipulasi penonton.
Sayangnya, sisa film tidak seberani itu. Alih-alih menyajikan realita pahit dari keluarga kelas pekerja dengan segala luka dan kompromi hidupnya, film ini memilih jalur mudah: menyuguhkan keluarga sebagai tempat kembali yang manis. Tidak ada ekonomi sebagai tekanan, tidak ada negara sebagai konteks, tidak ada sistem yang dipertanyakan. Padahal, dalam dunia nyata, keluarga adalah arena konflik antara cinta dan keterpaksaan, bukan sekadar tempat untuk berpelukan.
Film ini adalah contoh klasik sinema yang bermain aman. Ia tidak gagal secara teknis, tapi kehilangan nyali. Ia memilih air mata sebagai estetika, bukan sebagai hasil dari konfrontasi realitas. Ia menghindari kekacauan, padahal justru di dalam kekacauanlah kemanusiaan sering kali hadir paling jujur.
Dan pada akhirnya, “1 Kakak 7 Ponakan” terasa seperti album foto keluarga yang diedit terlalu rapi—semua terlihat utuh, hangat, tersenyum, tapi tidak pernah menunjukkan luka-luka di balik potret itu. Kita tahu ada duka, ada konflik, ada pertanyaan besar tentang beban menjadi tulang punggung keluarga di usia muda. Tapi film ini terlalu sopan untuk mengatakannya. Terlalu takut untuk marah. Terlalu jinak untuk menggugat. Dan dalam lanskap sinema Indonesia yang sedang lapar akan keberanian naratif, film ini justru memberi kenyamanan—bukan konfrontasi. Padahal, dalam cerita tentang keluarga, justru di situlah seharusnya ketidaknyamanan dimulai.